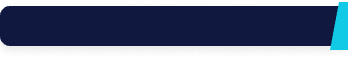Filter Bubble: Penjara Zona Nyaman yang Menyerang Mahasiswa Kekinian
loading...

Filter bubble bisa terjadi saat algoritma di media sosial dan internet membuat kita hanya disajikan fakta dari satu sudut pandang saja. Foto/cityam.com
A
A
A
JAKARTA - Lini masa Instagram saya berubah penuh, berisi tutorial pembuatan makanan. Kondisi yang mengharuskan saya untuk tetap di rumah, menyisakan banyak waktu yang kemudian digunakan untuk berselancar di media sosial.
Entah cerah atau hujan, lini masa saya tetap sama keesokannya. Seolah menjadi yang paling tahu tentang resep, saya selalu membagikannya kepada orang lain, meski saya sendiri tak hobi masak.
Lambat laun tersadarlah bahwa selama pandemi, saya tak tahu informasi apa-apa selain resep-resep ini. Belum lama saya tahu bahwa filter bubble lah yang telah membelenggu saya.
Filter bubble merupakan gelembung virtual penyaring informasi yang didapatkan seseorang dalam bermedia sosial. Aktivis internet, Eli Pariser, mengemukakan istilah ini sembilan tahun silam.
Baginya, algoritma media sosial seperti ini akan membuat seseorang terisolasi secara intelektual. Tidak terlepas bagi para mahasiswa di Indonesia. (
)
Pandemi COVID-19 bukan saja mengharuskan setiap orang untuk menjaga jarak ataupun tetap di rumah, tapi turut mengubah tatanan cara belajar, yang semula bertatap muka, beralih ke penggunaan model pendidikan jarak jauh.
![Filter Bubble: Penjara Zona Nyaman yang Menyerang Mahasiswa Kekinian]()
Foto: Getty Images
Cara ini paling tidak meminta setiap pembelajar mengaktifkan gawai untuk mendapatkan akses belajar. Pengaruh perubahan ini bukan saja berdampak pada segi ekonomi – harus menyediakan kuota internet lebih, tapi berkorelasi juga pada perubahan perilaku para mahasiswa.
Melansir dari data olahan Asosiasi Pengguna Jasa dan Internet Indonesia (APJII), pada 2018, kalangan milenial usia 20-35 tahun – rata-rata usia mahasiswa - 94,4 persen di antaranya telah terkoneksi internet, dan 98,2 persennya memiliki rata-rata penggunaan ponsel pintar selama 7 jam dalam sehari.
Riset ini dilakukan jauh sebelum pandemi terjadi, sehingga akan timbul kemungkinan besar peningkatan penggunaan ponsel pintar dalam sehari.
Belum lagi dengan jadwal kuliah yang tentatif, memungkinkan tiap mahasiswa harus siap sedia dengan ponsel dari pagi ke petang, pun petang ke pagi. Hal yang sama berimplikasi pada intensitas penggunaan media sosial, sebagai sarana mencari informasi atau sekadar menghibur diri di tengah pandemi.
![Filter Bubble: Penjara Zona Nyaman yang Menyerang Mahasiswa Kekinian]()
Foto: Getty Images
Media sosial adalah rumah dengan banyak pintu. Setiap orang punya preferensi untuk menentukan hendak ke mana ia menuju. Algoritma media membaca sesuatu yang diminati seseorang, sehinggga siapa pun bisa dimanjakan oleh keadaan.
Filter bubble bukan saja menjadi penyaring, dengan harapan seseorang bisa fokus pada minatnya. Bak penjara semu, mahasiswa sang pengguna media sosial telah terjebak di dalamnya. Namun, siapa yang sadar?
Beranggapan jadi Mayoritas
Gelembung penyaring ini akan menyajikan informasi yang sesuai dengan minat si pengguna media sosial. Secara umum orang akan merasa berada pada zona nyaman ketika mendapatkan sesuatu yang diinginkan, tanpa mempertimbangkan kualitas informasinya.
Misal saja, para pencinta konten junk food. Lini masa orang ini tentu akan dipenuhi oleh konten tersebut, sehingga ia akan melihat bahwa seisi media sosial berpihak padanya – sama-sama menyukai junk food.
Keadaan ini membuat seseorang beranggapan bahwa ia adalah mayoritas, yang punya banyak dukungan di media sosial, dan mendefinisikan dunia dari satu sudut pandang saja.
Sarang Hoaks
Filter bubble memberikan celah bagi siap apun untuk terperangkap pada hoaks. Nyatanya, algoritma media sosial didasari oleh jumlah suka, komentar, klik, unggah ulang, atau konten yang disimpan seseorang pada suatu topik.
Sebagai pasar bisnis yang terbuka, hoaks bisa muncul di mana saja, bahkan pada unggahan yang memiliki banyak respons. Tak jauh dari ungkapan Joseph Goebbels di awal, hoaks hadir dengan sampul bak berita valid.
![Filter Bubble: Penjara Zona Nyaman yang Menyerang Mahasiswa Kekinian]()
Foto:Fokusiert
Artinya, gelembung penyaring tidaklah benar-benar menyaring berita yang berkualitas dan valid. Setiap orang, termasuk mahasiswa berkemungkinan untuk memiliki lingkungan media sosial yang penuh hoaks.
Sebagai kelompok intelektual, keadaan ini merupakan tantangan yang perlu dikendalikan oleh keinginan. ( )
Polarisasi Warganet
“Sebuah dunia yang disusun dari kesamaan (familier), adalah tempat kita tak bisa belajar apa pun,” tutur Eli Pariser, melansir dari The Economist.
Karena dibangun atas kesamaan, gelembung ini mendorong seseorang untuk berkumpul dengan warganet dalam satu lingkup, dengan minat yang sama.
Kuatnya persamaan pandangan terhadap suatu topik membuat seseorang terpolarisasi dengan kelompok di sisi lawan. Ketika bertemu dengan orang lain yang tidak segelembung dengannya, ia akan menganggap bahwa mereka adalah minoritas, yang kemudian berdampak pada munculnya perilaku intoleran, perpecahan, sentimen, serta menolak adanya perbedaan.
![Filter Bubble: Penjara Zona Nyaman yang Menyerang Mahasiswa Kekinian]()
Foto: Janinsanfran/Flickr
Bukan mahasiswa kalau cuma berpangku tangan di tengah tantangan. Dampak gelembung virtual di atas berpeluang menghampiri siapa saja, terlebih mahasiswa yang mayoritas merupakan pengguna media sosial.
Yang Bisa Kita Lakukan
Intensitas penggunaan media sosial yang meningkat selama pandemi, memperlebar peluang filter bubble setiap orang. Apa antisipasinya?
Pertama, sengaja mencari informasi yang berlainan dengan minat, adalah langkah awal menghilangkan filter bubble. Cara ini memungkinkan seseorang kembali mendapatkan informasi yang lebih banyak dan variatif, sehingga berdampak pada perubahan perilaku untuk melihat sesuatu tidak dari satu sudut pandang saja.
Kedua, menerapkan perilaku berpikir kritis sangat dibutuhkan untuk memecahkan gelembung ini. Perilaku ini membawa seseorang untuk mengakar dari pertanyaan dan sikap skeptis, untuk menguji valid atau tidaknya suatu informasi.
“Berpikir kritis dan empati memungkinkan kita untuk melihat dunia bukan dengan kacamata ketakutan, tapi dengan kacamata keingintahuan,” ujar Emilia Tiurma, Senior Officer Indika Foundation saat menjadi narasumber kelas berpikir kritis.
![Filter Bubble: Penjara Zona Nyaman yang Menyerang Mahasiswa Kekinian]()
Foto: Twomeows/Getty Images
Kemampuan berpikir kritis mendorong pengguna media sosial untuk memilih dan memilah informasi. Jika sudah tahu informasi tersebut hoaks, pilihannya hanya dua, mengabaikannya, atau dengan mengajukan laporan ketidaktertarikan pada konten tersebut.
Pada Instagram misalnya, ketika berselancar di lini masa, pengguna hanya perlu memilih posting-an yang hendak disingkirkan filter bubble-nya, setelah itu pilih “titik tiga” di ujung kanan unggahan, kemudian pilih “tidak tertarik”.
Pengguna perlu melakukan hal ini pada beberapa konten serupa agar pemecahan gelembungnya lebih efisien. ( )
Setelah gelembung disingkirkan perlahan, cara selanjutnya adalah tetap teguh bersikap toleran. Ayu Kartika Dewi, salah satu co-founder SabangMerauke percaya bahwa toleransi dibagi ke dalam empat jenis.
![Filter Bubble: Penjara Zona Nyaman yang Menyerang Mahasiswa Kekinian]()
Foto: Erin Drago/Stocksy United
Toleransi pasif (selama seseorang tidak ganggu, tidak masalah), toleransi yang senang dengan perbedaan, toleransi yang senang merayakan perbedaan, dan toleransi yang melindungi perbedaan.
“Kita, tuh, jangan hanya bertoleransi pasif, tapi juga harus naik tingkat ke toleransi yang melindungi perbedaan,” ungkap Ayu.
Dengan sikap ini, setiap orang akan dengan lapang menerima perbedaan, tanpa menyudutkan satu sama lain, yang kemudian menjadi upaya penciptaan lingkungan media sosial yang lebih harmonis, punya empati, dan kritis.
Tito Tri Kadafi
Kontributor GenSINDO
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Instagram: @tokads
Lihat Juga: Rahasia Sukses Kampanye Kreatif: Tips Konten Efektif ala Hanssen Benjamin, Kreator TikTok
Entah cerah atau hujan, lini masa saya tetap sama keesokannya. Seolah menjadi yang paling tahu tentang resep, saya selalu membagikannya kepada orang lain, meski saya sendiri tak hobi masak.
Lambat laun tersadarlah bahwa selama pandemi, saya tak tahu informasi apa-apa selain resep-resep ini. Belum lama saya tahu bahwa filter bubble lah yang telah membelenggu saya.
Filter bubble merupakan gelembung virtual penyaring informasi yang didapatkan seseorang dalam bermedia sosial. Aktivis internet, Eli Pariser, mengemukakan istilah ini sembilan tahun silam.
Baginya, algoritma media sosial seperti ini akan membuat seseorang terisolasi secara intelektual. Tidak terlepas bagi para mahasiswa di Indonesia. (
Baca Juga
Pandemi COVID-19 bukan saja mengharuskan setiap orang untuk menjaga jarak ataupun tetap di rumah, tapi turut mengubah tatanan cara belajar, yang semula bertatap muka, beralih ke penggunaan model pendidikan jarak jauh.

Foto: Getty Images
Cara ini paling tidak meminta setiap pembelajar mengaktifkan gawai untuk mendapatkan akses belajar. Pengaruh perubahan ini bukan saja berdampak pada segi ekonomi – harus menyediakan kuota internet lebih, tapi berkorelasi juga pada perubahan perilaku para mahasiswa.
Melansir dari data olahan Asosiasi Pengguna Jasa dan Internet Indonesia (APJII), pada 2018, kalangan milenial usia 20-35 tahun – rata-rata usia mahasiswa - 94,4 persen di antaranya telah terkoneksi internet, dan 98,2 persennya memiliki rata-rata penggunaan ponsel pintar selama 7 jam dalam sehari.
Riset ini dilakukan jauh sebelum pandemi terjadi, sehingga akan timbul kemungkinan besar peningkatan penggunaan ponsel pintar dalam sehari.
Belum lagi dengan jadwal kuliah yang tentatif, memungkinkan tiap mahasiswa harus siap sedia dengan ponsel dari pagi ke petang, pun petang ke pagi. Hal yang sama berimplikasi pada intensitas penggunaan media sosial, sebagai sarana mencari informasi atau sekadar menghibur diri di tengah pandemi.

Foto: Getty Images
Media sosial adalah rumah dengan banyak pintu. Setiap orang punya preferensi untuk menentukan hendak ke mana ia menuju. Algoritma media membaca sesuatu yang diminati seseorang, sehinggga siapa pun bisa dimanjakan oleh keadaan.
Filter bubble bukan saja menjadi penyaring, dengan harapan seseorang bisa fokus pada minatnya. Bak penjara semu, mahasiswa sang pengguna media sosial telah terjebak di dalamnya. Namun, siapa yang sadar?
Beranggapan jadi Mayoritas
Gelembung penyaring ini akan menyajikan informasi yang sesuai dengan minat si pengguna media sosial. Secara umum orang akan merasa berada pada zona nyaman ketika mendapatkan sesuatu yang diinginkan, tanpa mempertimbangkan kualitas informasinya.
Misal saja, para pencinta konten junk food. Lini masa orang ini tentu akan dipenuhi oleh konten tersebut, sehingga ia akan melihat bahwa seisi media sosial berpihak padanya – sama-sama menyukai junk food.
Keadaan ini membuat seseorang beranggapan bahwa ia adalah mayoritas, yang punya banyak dukungan di media sosial, dan mendefinisikan dunia dari satu sudut pandang saja.
Sarang Hoaks
Filter bubble memberikan celah bagi siap apun untuk terperangkap pada hoaks. Nyatanya, algoritma media sosial didasari oleh jumlah suka, komentar, klik, unggah ulang, atau konten yang disimpan seseorang pada suatu topik.
Sebagai pasar bisnis yang terbuka, hoaks bisa muncul di mana saja, bahkan pada unggahan yang memiliki banyak respons. Tak jauh dari ungkapan Joseph Goebbels di awal, hoaks hadir dengan sampul bak berita valid.

Foto:Fokusiert
Artinya, gelembung penyaring tidaklah benar-benar menyaring berita yang berkualitas dan valid. Setiap orang, termasuk mahasiswa berkemungkinan untuk memiliki lingkungan media sosial yang penuh hoaks.
Sebagai kelompok intelektual, keadaan ini merupakan tantangan yang perlu dikendalikan oleh keinginan. ( )
Polarisasi Warganet
“Sebuah dunia yang disusun dari kesamaan (familier), adalah tempat kita tak bisa belajar apa pun,” tutur Eli Pariser, melansir dari The Economist.
Karena dibangun atas kesamaan, gelembung ini mendorong seseorang untuk berkumpul dengan warganet dalam satu lingkup, dengan minat yang sama.
Kuatnya persamaan pandangan terhadap suatu topik membuat seseorang terpolarisasi dengan kelompok di sisi lawan. Ketika bertemu dengan orang lain yang tidak segelembung dengannya, ia akan menganggap bahwa mereka adalah minoritas, yang kemudian berdampak pada munculnya perilaku intoleran, perpecahan, sentimen, serta menolak adanya perbedaan.

Foto: Janinsanfran/Flickr
Bukan mahasiswa kalau cuma berpangku tangan di tengah tantangan. Dampak gelembung virtual di atas berpeluang menghampiri siapa saja, terlebih mahasiswa yang mayoritas merupakan pengguna media sosial.
Yang Bisa Kita Lakukan
Intensitas penggunaan media sosial yang meningkat selama pandemi, memperlebar peluang filter bubble setiap orang. Apa antisipasinya?
Pertama, sengaja mencari informasi yang berlainan dengan minat, adalah langkah awal menghilangkan filter bubble. Cara ini memungkinkan seseorang kembali mendapatkan informasi yang lebih banyak dan variatif, sehingga berdampak pada perubahan perilaku untuk melihat sesuatu tidak dari satu sudut pandang saja.
Kedua, menerapkan perilaku berpikir kritis sangat dibutuhkan untuk memecahkan gelembung ini. Perilaku ini membawa seseorang untuk mengakar dari pertanyaan dan sikap skeptis, untuk menguji valid atau tidaknya suatu informasi.
“Berpikir kritis dan empati memungkinkan kita untuk melihat dunia bukan dengan kacamata ketakutan, tapi dengan kacamata keingintahuan,” ujar Emilia Tiurma, Senior Officer Indika Foundation saat menjadi narasumber kelas berpikir kritis.

Foto: Twomeows/Getty Images
Kemampuan berpikir kritis mendorong pengguna media sosial untuk memilih dan memilah informasi. Jika sudah tahu informasi tersebut hoaks, pilihannya hanya dua, mengabaikannya, atau dengan mengajukan laporan ketidaktertarikan pada konten tersebut.
Pada Instagram misalnya, ketika berselancar di lini masa, pengguna hanya perlu memilih posting-an yang hendak disingkirkan filter bubble-nya, setelah itu pilih “titik tiga” di ujung kanan unggahan, kemudian pilih “tidak tertarik”.
Pengguna perlu melakukan hal ini pada beberapa konten serupa agar pemecahan gelembungnya lebih efisien. ( )
Setelah gelembung disingkirkan perlahan, cara selanjutnya adalah tetap teguh bersikap toleran. Ayu Kartika Dewi, salah satu co-founder SabangMerauke percaya bahwa toleransi dibagi ke dalam empat jenis.

Foto: Erin Drago/Stocksy United
Toleransi pasif (selama seseorang tidak ganggu, tidak masalah), toleransi yang senang dengan perbedaan, toleransi yang senang merayakan perbedaan, dan toleransi yang melindungi perbedaan.
“Kita, tuh, jangan hanya bertoleransi pasif, tapi juga harus naik tingkat ke toleransi yang melindungi perbedaan,” ungkap Ayu.
Dengan sikap ini, setiap orang akan dengan lapang menerima perbedaan, tanpa menyudutkan satu sama lain, yang kemudian menjadi upaya penciptaan lingkungan media sosial yang lebih harmonis, punya empati, dan kritis.
Tito Tri Kadafi
Kontributor GenSINDO
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Instagram: @tokads
Lihat Juga: Rahasia Sukses Kampanye Kreatif: Tips Konten Efektif ala Hanssen Benjamin, Kreator TikTok
(it)