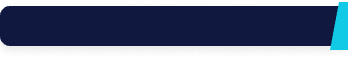Seperti Apa Konsultasi Ke Psikolog dan Psikiater? Ini Cerita Mereka yang Pernah Melakukannya
loading...

Konsultasi ke psikolog atau berobat ke psikiater bukanlah hal yang tabu dan justru dianjurkan untuk mengatasi masalah gangguan mental. Foto/iStockphoto
A
A
A
JAKARTA - Isu tentang kesehatan mental kini semakin menjadi perhatian masyarakat. Ditambah dengan adanya pandemi COVID-19 yang membuat sebagian orang merasa cemas, takut, dan berpikir secara berlebihan.
Dari data World Health Organization (WHO) sepanjang Juni-Agustus 2020, masalah kesehatan mental yang dialami anak-anak hingga remaja mencapai 72%, sementara pada orang dewasa mencapai 70%.
Sementara di Indonesia, dari artikel yang dirilis Kementerian Kesehatan pada 7 Oktober 2021, Dr Celestinus Eigya Munthe selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza menuturkan bahwa Indonesia memiliki orang dengan gangguan jiwa sekitar 1 dari 5 penduduk.
Ini artinya, sekitar 20% populasi di Indonesia mempunyai gejala dan potensi gangguan jiwa.
![Seperti Apa Konsultasi Ke Psikolog dan Psikiater? Ini Cerita Mereka yang Pernah Melakukannya]()
Foto: iStockphoto
Pada anak muda, masalah gangguan kesehatan mental bisa dimulai sejak remaja. Misalnya yang terjadi pada Devany Liora, 20, mahasiswi Binus University jurusan Desain Interior.
Pada 2019 saat ia masih duduk di bangku SMA kelas 3, Devany mengalami perubahan suasana hati (mood) secara drastis. Ini membuatnya jadi selalu ingin makan dan tidur saja setiap hari.
Dari sini, Devany akhirnya berkonsultasi kepada wali kelasnya, dan ia disarankan mengunjungi psikolog di sekolah. Ketika berkonsultasi, Devany diminta menjawab beberapa pertanyaan, lalu melakukan proses konseling selama kurang lebih 45 menit.
Tak Langsung Cocok dengan Psikolog
Sayangnya, alih-alih mendapatkan jawaban dari psikolog yang dikunjunginya itu, Devany justru merasa tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik. Malahan, ia merasakan gangguan mentalnya makin membuatnya terpuruk.
Saat itu, Devany mengaku hanya disarankan melakukan ibadah yang ia pun sudah tahu bahwa hal tersebut wajib dilakukan. "Aku merasa tidak menemukan jawaban sama sekali dari hasil konselingku bersama psikolog sekolah,” ujarnya.
![Seperti Apa Konsultasi Ke Psikolog dan Psikiater? Ini Cerita Mereka yang Pernah Melakukannya]()
Foto: iStockphoto
Pada akhirnya Devany memutuskan untuk melakukan konsultasi secara daring dengan psikiater lewat sebuah platform kesehatan. Dari situ, Devany mendapatkan obat berupa pil penenang untuk mempercepat proses penyembuhannya.
"Proses penyembuhannya cukup cepat, awal tahun 2021 aku dinyatakan sembuh dari gangguan mental dan tidak lagi melakukan konsultasi dengan psikiater," ujarnya.
Baca Juga: 7 Fakta dan Mitos tentang Kleptomania, Beda dengan Mengutil
Selain mengonsumsi obat, ia juga melakukan aktivitas yang mempercepat proses penyembuhannya. Ia aktif mengikuti perhimpunan mahasiswa di kampus dan organisasi lainnya untuk menyibukkan diri dan mengalihkan gangguan mentalnya.
Cerita dari Seorang Atlet
Seorang atlet yang erat kaitannya dengan fisik yang sehat pun tak berarti bebas dari masalah penyakit mental. Ini terjadi pada seorang atlet golf perempuan AA, 20. AA juga adalah mahasiswi Jurusan Komunikasi dan bekerja.
Pada Maret 2021, AA didiagnosis memiliki penyakit mental post-traumatic stress disorder(PTSD). Ini adalah bentuk gangguan kecemasan dan ketakutan yang berlebihan setelah mengalami peristiwa traumatis pada masa lalu.
Sejak saat itu, ia rutin berkonsultasi ke dua orang psikolog sekaligus. Satu psikolog untuk membantunya menangani masalah gangguan mental. Sementara satu lagi adalah psikolog mental coach untuk membantu AA berlatih bermain golf dengan gangguan mental yang ia miliki.
“Ada satu proses konsultasi yang menarik bagi aku, yaitu aku disuruh gambar dengan pensil warna tentang apa yang terlintas di otak aku pertama kali ketika mendengarkan sebuah lagu yang diputarkan oleh psikolog," cerita AA.
Butuh waktu lama untuk AA merasa menjadi lebih baik. Ini karena ia mengaku memiliki sifat keras kepala yang bisa memicu penyakitnya itu.
![Seperti Apa Konsultasi Ke Psikolog dan Psikiater? Ini Cerita Mereka yang Pernah Melakukannya]()
Foto: iStockphoto
AA mengatakan, ketika gangguan mentalnya menyerang secara tiba-tiba, maka dia akan mendengarkan murottal (rekaman orang mengaji) atau mendengarkan musik favoritnya. “Aku juga suka ngaca di depan cermin sambil ngomong sama diri sendiri bahwa enggak apa-apa merasa enggak baik-baik aja," katanya.
Ia juga sering mengepalkan tangannya untuk menyalurkan emosi. "Kalau masalahnya enggak terselesaikan juga, biasanya aku langsung menghubungi psikolog aku," imbuhnya.
Tak Perlu Takut Stigma
Sementara Dian, 23,mahasiswi Universitas Padjajaran yang mengalami anxiety disorder (gejala kecemasan yang membawa kepanikan dan gangguan pascastres dari peristiwa masa lalu) pernah melakukan konsultasi daring.
Pada awal proses konsultasi, Dian diminta menceritakan semua unek-unek atau permasalahan yang terjadi dan bagaimana perasaan yang dialami pada saat itu. Dari situ Dian disarakan beberapa hal untuk mengatasi masalahnya.
“Aku benar-benar dikasih tau bahwa menjalani hidup harus dengan rileks dan aku ditantang untuk mencoba menyisihkan waktu ku dari kehidupan sehari-hari untuk olahraga, menenangkan pikiran dan pernapasan jika serangan panik muncul tiba-tiba,” kata Dian yang saat ini masih rutin melakukan konsultasi dengan psikolognya.
![Seperti Apa Konsultasi Ke Psikolog dan Psikiater? Ini Cerita Mereka yang Pernah Melakukannya]()
Foto: Bigstock
Perihal stigma yang menimpa penderita gangguan mental, Devany mengatakan kekecewaannya. "Perlu digarisbawahi bahwa penyakit mental tidak seperti penyakit fisik, karena jika orang sudah mengalami gangguan mental, maka fisikinya pun akan ikut sakit," katanya.
Baca Juga: 3 Perbedaan Besar Business Proposal dengan Webtoon-nya yang Membuat Penonton Kecewa
Sementara AA mengatakan ia berusaha untuk mengabaikan anggapan buruk tentang penderita masalah kesehatan mental.
“Kita cuma punya dua tangan dan enggak mungkin dua tangan kita ini cukup untuk menutup mulut mereka yang berasumsi bahwa berkunjung ke psikolog merupakan hal yang gila. Yang kita lakukan sekarang hanyalah menutup kedua telinga kita dengan tangan kita sendiri untuk menjadi diri kita yang lebih baik lagi, karena hidupku adalah hidupku, dan hidupmu adalah hidup kamu," kata AA.
Amatu Syukur Naimah
Kontributor GenSINDO
Politeknik Negeri Media Kreatif
Instagram: @amatusyukur_
Dari data World Health Organization (WHO) sepanjang Juni-Agustus 2020, masalah kesehatan mental yang dialami anak-anak hingga remaja mencapai 72%, sementara pada orang dewasa mencapai 70%.
Sementara di Indonesia, dari artikel yang dirilis Kementerian Kesehatan pada 7 Oktober 2021, Dr Celestinus Eigya Munthe selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza menuturkan bahwa Indonesia memiliki orang dengan gangguan jiwa sekitar 1 dari 5 penduduk.
Ini artinya, sekitar 20% populasi di Indonesia mempunyai gejala dan potensi gangguan jiwa.

Foto: iStockphoto
Pada anak muda, masalah gangguan kesehatan mental bisa dimulai sejak remaja. Misalnya yang terjadi pada Devany Liora, 20, mahasiswi Binus University jurusan Desain Interior.
Pada 2019 saat ia masih duduk di bangku SMA kelas 3, Devany mengalami perubahan suasana hati (mood) secara drastis. Ini membuatnya jadi selalu ingin makan dan tidur saja setiap hari.
Dari sini, Devany akhirnya berkonsultasi kepada wali kelasnya, dan ia disarankan mengunjungi psikolog di sekolah. Ketika berkonsultasi, Devany diminta menjawab beberapa pertanyaan, lalu melakukan proses konseling selama kurang lebih 45 menit.
Tak Langsung Cocok dengan Psikolog
Sayangnya, alih-alih mendapatkan jawaban dari psikolog yang dikunjunginya itu, Devany justru merasa tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik. Malahan, ia merasakan gangguan mentalnya makin membuatnya terpuruk.
Saat itu, Devany mengaku hanya disarankan melakukan ibadah yang ia pun sudah tahu bahwa hal tersebut wajib dilakukan. "Aku merasa tidak menemukan jawaban sama sekali dari hasil konselingku bersama psikolog sekolah,” ujarnya.

Foto: iStockphoto
Pada akhirnya Devany memutuskan untuk melakukan konsultasi secara daring dengan psikiater lewat sebuah platform kesehatan. Dari situ, Devany mendapatkan obat berupa pil penenang untuk mempercepat proses penyembuhannya.
"Proses penyembuhannya cukup cepat, awal tahun 2021 aku dinyatakan sembuh dari gangguan mental dan tidak lagi melakukan konsultasi dengan psikiater," ujarnya.
Baca Juga: 7 Fakta dan Mitos tentang Kleptomania, Beda dengan Mengutil
Selain mengonsumsi obat, ia juga melakukan aktivitas yang mempercepat proses penyembuhannya. Ia aktif mengikuti perhimpunan mahasiswa di kampus dan organisasi lainnya untuk menyibukkan diri dan mengalihkan gangguan mentalnya.
Cerita dari Seorang Atlet
Seorang atlet yang erat kaitannya dengan fisik yang sehat pun tak berarti bebas dari masalah penyakit mental. Ini terjadi pada seorang atlet golf perempuan AA, 20. AA juga adalah mahasiswi Jurusan Komunikasi dan bekerja.
Pada Maret 2021, AA didiagnosis memiliki penyakit mental post-traumatic stress disorder(PTSD). Ini adalah bentuk gangguan kecemasan dan ketakutan yang berlebihan setelah mengalami peristiwa traumatis pada masa lalu.
Sejak saat itu, ia rutin berkonsultasi ke dua orang psikolog sekaligus. Satu psikolog untuk membantunya menangani masalah gangguan mental. Sementara satu lagi adalah psikolog mental coach untuk membantu AA berlatih bermain golf dengan gangguan mental yang ia miliki.
“Ada satu proses konsultasi yang menarik bagi aku, yaitu aku disuruh gambar dengan pensil warna tentang apa yang terlintas di otak aku pertama kali ketika mendengarkan sebuah lagu yang diputarkan oleh psikolog," cerita AA.
Butuh waktu lama untuk AA merasa menjadi lebih baik. Ini karena ia mengaku memiliki sifat keras kepala yang bisa memicu penyakitnya itu.

Foto: iStockphoto
AA mengatakan, ketika gangguan mentalnya menyerang secara tiba-tiba, maka dia akan mendengarkan murottal (rekaman orang mengaji) atau mendengarkan musik favoritnya. “Aku juga suka ngaca di depan cermin sambil ngomong sama diri sendiri bahwa enggak apa-apa merasa enggak baik-baik aja," katanya.
Ia juga sering mengepalkan tangannya untuk menyalurkan emosi. "Kalau masalahnya enggak terselesaikan juga, biasanya aku langsung menghubungi psikolog aku," imbuhnya.
Tak Perlu Takut Stigma
Sementara Dian, 23,mahasiswi Universitas Padjajaran yang mengalami anxiety disorder (gejala kecemasan yang membawa kepanikan dan gangguan pascastres dari peristiwa masa lalu) pernah melakukan konsultasi daring.
Pada awal proses konsultasi, Dian diminta menceritakan semua unek-unek atau permasalahan yang terjadi dan bagaimana perasaan yang dialami pada saat itu. Dari situ Dian disarakan beberapa hal untuk mengatasi masalahnya.
“Aku benar-benar dikasih tau bahwa menjalani hidup harus dengan rileks dan aku ditantang untuk mencoba menyisihkan waktu ku dari kehidupan sehari-hari untuk olahraga, menenangkan pikiran dan pernapasan jika serangan panik muncul tiba-tiba,” kata Dian yang saat ini masih rutin melakukan konsultasi dengan psikolognya.

Foto: Bigstock
Perihal stigma yang menimpa penderita gangguan mental, Devany mengatakan kekecewaannya. "Perlu digarisbawahi bahwa penyakit mental tidak seperti penyakit fisik, karena jika orang sudah mengalami gangguan mental, maka fisikinya pun akan ikut sakit," katanya.
Baca Juga: 3 Perbedaan Besar Business Proposal dengan Webtoon-nya yang Membuat Penonton Kecewa
Sementara AA mengatakan ia berusaha untuk mengabaikan anggapan buruk tentang penderita masalah kesehatan mental.
“Kita cuma punya dua tangan dan enggak mungkin dua tangan kita ini cukup untuk menutup mulut mereka yang berasumsi bahwa berkunjung ke psikolog merupakan hal yang gila. Yang kita lakukan sekarang hanyalah menutup kedua telinga kita dengan tangan kita sendiri untuk menjadi diri kita yang lebih baik lagi, karena hidupku adalah hidupku, dan hidupmu adalah hidup kamu," kata AA.
Amatu Syukur Naimah
Kontributor GenSINDO
Politeknik Negeri Media Kreatif
Instagram: @amatusyukur_
(ita)