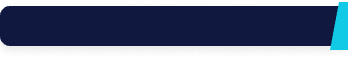Review Film Seribu Kunang-Kunang di Jakarta: Kunang-Kunang, Joko Pinurbo, dan Etnis Tionghoa
loading...

Film pendek Seribu Kunang-Kunang mengadopsi kisah dari puisi Joko Pinurbo. Foto/Tomat
A
A
A
JAKARTA - Setidaknya ada tiga puisi dari penyair Joko Pinurbo yang menyertakan soal kunang-kunang sebagai pusat semestanya bercerita.
Gadis kecil jalan seorang
dengan payung hitam.
Tangannya gemetar
menjinjing bulan
dalam keranjang.
Dalam puisi berjudul Kunang-Kunang, Joko menyertakan kunang-kunang sebagai medium untuk menyimpan kenangan, juga sebagai pembawa cahaya.
Dalam puisinya yang lain yang berjudul Tahi Lalat, Joko bercerita soal hubungan ibu dan anak, dan menggunakan kunang-kunang sebagai kata ganti untuk mengidentifikasi sesuatu yang disayangi si anak pada ibunya. Dan tentu saja pada puisi berjudul Seribu Kunang-Kunang di Jakarta, saat ia bermain-main dengan metafora yang menarik untuk ditafsirkan.
Kehadiran kunang-kunang bisa dimaknai dari beragam sudut pandang. Saat memproduseri film SILARIANG: Cinta Yang (Tak) Direstui, kami juga menyentil soal kehadiran kunang-kunang sebagai pembawa harapan dalam sebuah dialog: “Menurut kepercayaan kuno, kunang-kunang hanya mau muncul di depan orang yang masih punya harapan”.
Dialog itu seakan memberi energi baru pada Zulaikha yang letih setelah mengikuti kekasihnya, Yusuf, melarikan diri dari keluarganya setelah tak merestui pernikahan siri mereka.
![Review Film Seribu Kunang-Kunang di Jakarta: Kunang-Kunang, Joko Pinurbo, dan Etnis Tionghoa]()
Foto: Tomat
Ketika dialihwahanakan menjadi film pendek, Seribu Kunang-Kunang di Jakarta didorong untuk memenuhi sejumlah visi dari pembuatnya. Gadis kecil yang dihadirkan dari etnis Tionghoa dan latar belakang tahun 1998 tentu saja dipilih dengan cermat untuk menyampaikan pesan tertentu.
Di atas kertas menarik untuk melihat pilihan kreatif dari pembuat filmnya, tapi perlu diingat bahwa film adalah medium visual. Untuk menekankan pesan agar sampai dengan baik ke benak penonton, maka perlu untuk memperlihatkan, bukan sekadar mendialogkannya.
Keterkaitan antara tahun 1998 dan etnis Tionghoa tentu selalu menarik untuk dibahas. Kita mengingat tahun itu menjadi salah satu peristiwa paling kelam di negeri ini, ketika negeri sedang berubah, menuju porak poranda, dan banyak orang di dalamnya yang terseret tak tentu arah. Termasuk saudara-saudara kita dari etnis Tionghoa yang harus menyelamatkan diri, melakukan segala untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga mereka.
![Review Film Seribu Kunang-Kunang di Jakarta: Kunang-Kunang, Joko Pinurbo, dan Etnis Tionghoa]()
Foto: Tomat
Tapi menyajikannya hanya lewat petikan siaran radio dan dari sudut pandang seorang gadis kecil tentu saja tak cukup. Dua hal itu terlalu besar untuk disederhanakan dalam sebuah pilihan kreatif yang diambil pembuatnya. Jadinya justru membuat film ini terlihat terlalu ambisius untuk membawa gagasan-gagasan besar, tapi kehilangan daya kreatif untuk mengeksekusinya agar gagasan-gagasan itu tak mengalami erosi.
Juga pendekatan kreatif untuk menjadikan tokoh utama seorang penyair membuat film pendekSeribu Kunang-Kunang di Jakarta terasa tak berusaha mencelat keluar lebih jauh dari pemaknaannya sebagai puisi. Bisa jadi membuat filmnya memberi jarak tertentu kepada penonton.
Kita melihat penyair bukan sebagai “seseorang dari kita”, kita melihatnya sebagai “seseorang yang lain”. Padahal ketika melakukan alih wahana, si pembuat tak punya utang apa pun kepada materi aslinya.
Payung hitam diubahnya menjadi merah untuk lebih menegaskan soal negeri yang diamuk kemarahan pun sesungguhnya tak masalah. Atau soal menjinjing bulan yang juga bisa diterjemahkan lebih kreatif daripada sekadar menyamakannya dengan yang tertulis dalam puisi.
![Review Film Seribu Kunang-Kunang di Jakarta: Kunang-Kunang, Joko Pinurbo, dan Etnis Tionghoa]()
Foto: Tomat
Padahal sebagai puisi, Seribu Kunang-Kunang di Jakarta punya daya pikat dan magis yang luar biasa. Metafora yang malang melintang di dalamnya menunggu tafsir yang lebih liar yang akan menjadikan alih wahananya sebagai film memiliki daya ledak yang melebihi yang dilakukan puisi, bukan malah mereduksinya. Jika lebih kreatif, bisa saja si pembuat menggabungkan soal kunang-kunang dengan puisi Joko lainnya seperti yang saya sebutkan pada pembuka tulisan ini.
Tapi kita perlu mengapresiasi niat baik dari si pembuat untuk bercerita tak hanya soal kunang-kunang, tapi juga soal kenang-kenang sebagaimana yang dituturkan Joko. Kita diajak mengenang kembali sebuah masa yang terjadi pada 25 tahun silam ketika negeri ini terpecah belah dan etnis Tionghoa sering kali terhimpit di tengahnya.
Percayalah yang terjadi pada 1998 tak sesederhana sebagaimana yang banyak dituturkan via puisi, novel, hingga film. Kompleksitas yang terjadi melingkupinya melebihi apa pun yang pernah kita bayangkan, dan hingga hari ini masih banyak tabir misteri yang menutupinya dan belum tersibak.
Namun kelak kita akan selalu mengingat bahwa pada sebuah malam Jakarta yang dipenuhi polusi cahaya, ada saat kita bisa bertemu dengan seribu kunang-kunang. Yang datang entah dengan makna apa. Bisa saja untuk menyimpan kenangan, bisa juga untuk menyampaikan pesan, bisa pula untuk mengingatkan kita kembali bahwa setelah kehidupan kita porak poranda, selalu ada harapan untuk menatanya kembali.
Saat ia pamit pergi ngembara, ayahnya membekalinya
dengan sebutir kenang-kenang dalam botol.
“Pandanglah dengan mesra kenang-kenang ini
saat kau sedang gelap atau mati kata;
maka kunang-kunang akan datang memberimu cahaya
Ichwan Persada
Sutradara/produser/penulis skenario, pernah menjadi dosen di Universitas Padjajaran dan SAE Institute, bisa dikontak via Instagram @ichwanpersada
Gadis kecil jalan seorang
dengan payung hitam.
Tangannya gemetar
menjinjing bulan
dalam keranjang.
Dalam puisi berjudul Kunang-Kunang, Joko menyertakan kunang-kunang sebagai medium untuk menyimpan kenangan, juga sebagai pembawa cahaya.
Dalam puisinya yang lain yang berjudul Tahi Lalat, Joko bercerita soal hubungan ibu dan anak, dan menggunakan kunang-kunang sebagai kata ganti untuk mengidentifikasi sesuatu yang disayangi si anak pada ibunya. Dan tentu saja pada puisi berjudul Seribu Kunang-Kunang di Jakarta, saat ia bermain-main dengan metafora yang menarik untuk ditafsirkan.
Kehadiran kunang-kunang bisa dimaknai dari beragam sudut pandang. Saat memproduseri film SILARIANG: Cinta Yang (Tak) Direstui, kami juga menyentil soal kehadiran kunang-kunang sebagai pembawa harapan dalam sebuah dialog: “Menurut kepercayaan kuno, kunang-kunang hanya mau muncul di depan orang yang masih punya harapan”.
Dialog itu seakan memberi energi baru pada Zulaikha yang letih setelah mengikuti kekasihnya, Yusuf, melarikan diri dari keluarganya setelah tak merestui pernikahan siri mereka.

Foto: Tomat
Ketika dialihwahanakan menjadi film pendek, Seribu Kunang-Kunang di Jakarta didorong untuk memenuhi sejumlah visi dari pembuatnya. Gadis kecil yang dihadirkan dari etnis Tionghoa dan latar belakang tahun 1998 tentu saja dipilih dengan cermat untuk menyampaikan pesan tertentu.
Di atas kertas menarik untuk melihat pilihan kreatif dari pembuat filmnya, tapi perlu diingat bahwa film adalah medium visual. Untuk menekankan pesan agar sampai dengan baik ke benak penonton, maka perlu untuk memperlihatkan, bukan sekadar mendialogkannya.
Keterkaitan antara tahun 1998 dan etnis Tionghoa tentu selalu menarik untuk dibahas. Kita mengingat tahun itu menjadi salah satu peristiwa paling kelam di negeri ini, ketika negeri sedang berubah, menuju porak poranda, dan banyak orang di dalamnya yang terseret tak tentu arah. Termasuk saudara-saudara kita dari etnis Tionghoa yang harus menyelamatkan diri, melakukan segala untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga mereka.

Foto: Tomat
Tapi menyajikannya hanya lewat petikan siaran radio dan dari sudut pandang seorang gadis kecil tentu saja tak cukup. Dua hal itu terlalu besar untuk disederhanakan dalam sebuah pilihan kreatif yang diambil pembuatnya. Jadinya justru membuat film ini terlihat terlalu ambisius untuk membawa gagasan-gagasan besar, tapi kehilangan daya kreatif untuk mengeksekusinya agar gagasan-gagasan itu tak mengalami erosi.
Juga pendekatan kreatif untuk menjadikan tokoh utama seorang penyair membuat film pendekSeribu Kunang-Kunang di Jakarta terasa tak berusaha mencelat keluar lebih jauh dari pemaknaannya sebagai puisi. Bisa jadi membuat filmnya memberi jarak tertentu kepada penonton.
Kita melihat penyair bukan sebagai “seseorang dari kita”, kita melihatnya sebagai “seseorang yang lain”. Padahal ketika melakukan alih wahana, si pembuat tak punya utang apa pun kepada materi aslinya.
Payung hitam diubahnya menjadi merah untuk lebih menegaskan soal negeri yang diamuk kemarahan pun sesungguhnya tak masalah. Atau soal menjinjing bulan yang juga bisa diterjemahkan lebih kreatif daripada sekadar menyamakannya dengan yang tertulis dalam puisi.

Foto: Tomat
Padahal sebagai puisi, Seribu Kunang-Kunang di Jakarta punya daya pikat dan magis yang luar biasa. Metafora yang malang melintang di dalamnya menunggu tafsir yang lebih liar yang akan menjadikan alih wahananya sebagai film memiliki daya ledak yang melebihi yang dilakukan puisi, bukan malah mereduksinya. Jika lebih kreatif, bisa saja si pembuat menggabungkan soal kunang-kunang dengan puisi Joko lainnya seperti yang saya sebutkan pada pembuka tulisan ini.
Tapi kita perlu mengapresiasi niat baik dari si pembuat untuk bercerita tak hanya soal kunang-kunang, tapi juga soal kenang-kenang sebagaimana yang dituturkan Joko. Kita diajak mengenang kembali sebuah masa yang terjadi pada 25 tahun silam ketika negeri ini terpecah belah dan etnis Tionghoa sering kali terhimpit di tengahnya.
Percayalah yang terjadi pada 1998 tak sesederhana sebagaimana yang banyak dituturkan via puisi, novel, hingga film. Kompleksitas yang terjadi melingkupinya melebihi apa pun yang pernah kita bayangkan, dan hingga hari ini masih banyak tabir misteri yang menutupinya dan belum tersibak.
Namun kelak kita akan selalu mengingat bahwa pada sebuah malam Jakarta yang dipenuhi polusi cahaya, ada saat kita bisa bertemu dengan seribu kunang-kunang. Yang datang entah dengan makna apa. Bisa saja untuk menyimpan kenangan, bisa juga untuk menyampaikan pesan, bisa pula untuk mengingatkan kita kembali bahwa setelah kehidupan kita porak poranda, selalu ada harapan untuk menatanya kembali.
Saat ia pamit pergi ngembara, ayahnya membekalinya
dengan sebutir kenang-kenang dalam botol.
“Pandanglah dengan mesra kenang-kenang ini
saat kau sedang gelap atau mati kata;
maka kunang-kunang akan datang memberimu cahaya
Ichwan Persada
Sutradara/produser/penulis skenario, pernah menjadi dosen di Universitas Padjajaran dan SAE Institute, bisa dikontak via Instagram @ichwanpersada
(ita)