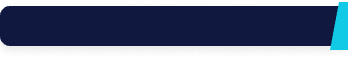CERMIN: Tuhan (Tak) Ada di Guantanamo
loading...

The Mauritanian memperlihatkan betapa brutalnya hukum yang berdiri atas nama ketakutan, yang tak pernah mencoba adil, dan yang tak bisa melihat dengan jernih. Foto/STX Entertainment
A
A
A
JAKARTA - “Apa gunanya shalat jika kamu berada di sini? Percayalah, itu tak ada gunanya sama sekali.”
Tahun 2001. Saya masih bergumul dengan mata kuliah yang sulit dan Amerika Serikat diserang teroris.
11 September 2001. Sudah berlalu hampir 21 tahun tapi Amerika masih takkan lupa bagaimana peristiwa di Selasa pagi itu meninggalkan luka teramat dalam hingga hari ini. Empat pesawat dibajak teroris dan menabrak dua gedung ikonik yang melambangkan kekuatan ekonomi, politik, dan militer mereka.
Dua gedung itu hancur luluh lantak bersama dengan tewasnya hampir 3.000 orang. Serangan itu masih menjadi serangan terbesar yang pernah menimpa Amerika dan konsekuensinya masih terasa hingga kini.
![CERMIN: Tuhan (Tak) Ada di Guantanamo]()
Foto: STX Entertainment
Salah satu konsekuensi itu bernama Mohamedou Ould Slahi, seorang warga Mauritania yang ditahan semena-semena selama 14 tahun 2 bulan sejak 2002 di bawah kepemimpinan dua presiden. Dalam cuplikan buku Guantanamo Diary yang dijadikan adegan pembuka film The Mauritanian, kita melihat Mohamedou didatangi polisi yang memintanya datang ke markas.
Salah satu polisi membocorkan tuduhan yang mungkin dialamatkan padanya. Namun, Mohamedou mencoba berbaik sangka. Dia tak bisa menutupi rasa waswasnya, begitupun dia mencoba menenangkan ibunya bahwa permintaan itu semata hanyalah persoalan salah paham belaka.
Dia bahkan sempat berkelakar pada ibunya agar menyisakan makanan favoritnya yang belum sempat dicicipinya. Siapa yang menyangka itu adalah kali terakhir Mohamedou bertemu dengan ibunya.
Sejak 11 September 2001, Amerika dilanda ketakutan luar biasa. Ketakutan itu diperangkap dalam sebuah penjara kebal hukum berlokasi di Guantanamo, Kuba. Sayangnya, memang sering kali ketakutan itu datang membabi buta, dia bertindak serampangan, mengadili yang tak bersalah dan sewenang-wenang menggunakan tangan besi demi mengelola rasa takut itu.
Korbannya adalah ribuan orang terpenjara atas nama terorisme di sana seperti Mohamedou. Dengan gamblang, The Mauritanian memperlihatkan betapa brutalnya hukum yang berdiri atas nama ketakutan.
Baca Juga: CERMIN: Perjalanan Membawamu
Hukum yang tak pernah mencoba adil, hukum yang tak bisa melihat dengan jernih dan hukum yang tak mungkin berlaku jujur. Hukum itu melucuti hak dasar manusia dan memperlakukannya sebagai objek, bahkan untuk sebuah alasan yang tak bisa disebutkan.
Sejak 11 September 2001, ketakutan dan rasa benci hidup harmonis di Amerika. Segala berbau Arab dianggap identik dengan terorisme, segala berbau Islam dengan mudah dicium dengan prasangka buruk dan kita tahu ujungnya adalah kesewenang-wenangan.
Kesewenang-wenangan itu dipelihara puluhan tahun. Tak terhitung berapa banyak orang yang dijebloskan ke Guantanamo tanpa tahu tuduhan apa yang dialamatkan kepada mereka.
Juga tak terhitung berapa banyak keluarga yang menderita karena tak pernah tahu nasib salah satu anggota keluarga mereka yang menghilang begitu saja. Tak terbilang bagaimana rasanya menjadi ibu dari para tahanan yang tak pernah melihat putranya selama bertahun-tahun dan terus memelihara harapan hingga harapan itu mati bersama mereka. Seperti ibu Mohamedou.
![CERMIN: Tuhan (Tak) Ada di Guantanamo]()
Foto: STX Entertainment
Ketakutan dan rasa benci dengan mudah menjadi alasan bagi Amerika untuk membuat garis batas jelas: “kami” dan “bukan kami”. Seakan garis batas itu mudah dibuat. Seakan “kami” hanya identik dengan warna kulit dan agama tertentu. Padahal Amerika pun tahu tak mudah mengidentifikasi diri sebagai “bukan kami”.
Bagaimana dengan warga Amerika keturunan Pakistan dan beragama Islam yang juga menjadi korban dari serangan biadab itu? Bagaimana pula dengan segelintir warga Amerika yang mensyukuri serangan itu sebagai “ujian bagi kesombongan Amerika”?
Dalam buku Catatan Pinggir, Goenawan Mohamad menyebut Guantanamo sebagai “tempat gelap sejenis nihilisme”. Di sini, di penjara Guantanamo, masa depan para tahanan tiba-tiba menjadi gelap.
Tak ada seorang pun yang bisa menyodorkan secercah cahaya kepada mereka untuk membuat masa depan kembali menjadi terang. Di titik ini, mereka bisa percaya Tuhan atau tidak sama sekali. Mereka juga bisa percaya bahwa sama sekali tak ada harapan atau bisa saja Tuhan mengirim malaikat berwujud pengacara hak asasi manusia bernama Nancy Hollander.
Baca Juga: Drama Korea yang Ratingnya Kecil tapi Menang Drama Terbaik Baeksang Arts Awards
Di Guantanamo, Mohamedou menjalani hukumannya dengan tabah. Awalnya dia syok, keimanannya terguncang hingga titik nadir sampai akhirnya dia pasrah dan berserah.
Dalam sebuah dialog yang tercantum di bagian paling atas tulisan ini, kita tahu Mohamedou menaruh harapan sepenuhnya pada Tuhan. Seseorang dengan nama alias Marseille, yang berbicara dengannya saat berada di luar bangunan penjara dengan pengamanan maksimum itu, meragukan gunanya untuk tetap menjalankan ibadah di tempat terkutuk seperti Guantanamo.
Namun Mohamedou tahu, Tuhan masih ada di sana, bersamanya, dan ribuan orang yang tak bersalah.
THE MAURITANIAN
Produser: Adam Ackland, Michael Bronner, Leah Clarke, Benedict Cumberbatch, Christine Holder, Mark Holder, Beatriz Levin, Lloyd Levin, Branwen Prestwood Smith
Sutradara: Kevin Macdonald
Penulis Skenario: M.B. Traven, Rory Haines, Sohrab Noshirvani
Pemain: Jodie Foster, Tahar Rahim, Benedict Cumberbatch
Ichwan Persada
Sutradara/produser/penulis skenario, pernah menjadi dosen di Universitas Padjajaran dan SAE Institute
Tahun 2001. Saya masih bergumul dengan mata kuliah yang sulit dan Amerika Serikat diserang teroris.
11 September 2001. Sudah berlalu hampir 21 tahun tapi Amerika masih takkan lupa bagaimana peristiwa di Selasa pagi itu meninggalkan luka teramat dalam hingga hari ini. Empat pesawat dibajak teroris dan menabrak dua gedung ikonik yang melambangkan kekuatan ekonomi, politik, dan militer mereka.
Dua gedung itu hancur luluh lantak bersama dengan tewasnya hampir 3.000 orang. Serangan itu masih menjadi serangan terbesar yang pernah menimpa Amerika dan konsekuensinya masih terasa hingga kini.

Foto: STX Entertainment
Salah satu konsekuensi itu bernama Mohamedou Ould Slahi, seorang warga Mauritania yang ditahan semena-semena selama 14 tahun 2 bulan sejak 2002 di bawah kepemimpinan dua presiden. Dalam cuplikan buku Guantanamo Diary yang dijadikan adegan pembuka film The Mauritanian, kita melihat Mohamedou didatangi polisi yang memintanya datang ke markas.
Salah satu polisi membocorkan tuduhan yang mungkin dialamatkan padanya. Namun, Mohamedou mencoba berbaik sangka. Dia tak bisa menutupi rasa waswasnya, begitupun dia mencoba menenangkan ibunya bahwa permintaan itu semata hanyalah persoalan salah paham belaka.
Dia bahkan sempat berkelakar pada ibunya agar menyisakan makanan favoritnya yang belum sempat dicicipinya. Siapa yang menyangka itu adalah kali terakhir Mohamedou bertemu dengan ibunya.
Sejak 11 September 2001, Amerika dilanda ketakutan luar biasa. Ketakutan itu diperangkap dalam sebuah penjara kebal hukum berlokasi di Guantanamo, Kuba. Sayangnya, memang sering kali ketakutan itu datang membabi buta, dia bertindak serampangan, mengadili yang tak bersalah dan sewenang-wenang menggunakan tangan besi demi mengelola rasa takut itu.
Korbannya adalah ribuan orang terpenjara atas nama terorisme di sana seperti Mohamedou. Dengan gamblang, The Mauritanian memperlihatkan betapa brutalnya hukum yang berdiri atas nama ketakutan.
Baca Juga: CERMIN: Perjalanan Membawamu
Hukum yang tak pernah mencoba adil, hukum yang tak bisa melihat dengan jernih dan hukum yang tak mungkin berlaku jujur. Hukum itu melucuti hak dasar manusia dan memperlakukannya sebagai objek, bahkan untuk sebuah alasan yang tak bisa disebutkan.
Sejak 11 September 2001, ketakutan dan rasa benci hidup harmonis di Amerika. Segala berbau Arab dianggap identik dengan terorisme, segala berbau Islam dengan mudah dicium dengan prasangka buruk dan kita tahu ujungnya adalah kesewenang-wenangan.
Kesewenang-wenangan itu dipelihara puluhan tahun. Tak terhitung berapa banyak orang yang dijebloskan ke Guantanamo tanpa tahu tuduhan apa yang dialamatkan kepada mereka.
Juga tak terhitung berapa banyak keluarga yang menderita karena tak pernah tahu nasib salah satu anggota keluarga mereka yang menghilang begitu saja. Tak terbilang bagaimana rasanya menjadi ibu dari para tahanan yang tak pernah melihat putranya selama bertahun-tahun dan terus memelihara harapan hingga harapan itu mati bersama mereka. Seperti ibu Mohamedou.

Foto: STX Entertainment
Ketakutan dan rasa benci dengan mudah menjadi alasan bagi Amerika untuk membuat garis batas jelas: “kami” dan “bukan kami”. Seakan garis batas itu mudah dibuat. Seakan “kami” hanya identik dengan warna kulit dan agama tertentu. Padahal Amerika pun tahu tak mudah mengidentifikasi diri sebagai “bukan kami”.
Bagaimana dengan warga Amerika keturunan Pakistan dan beragama Islam yang juga menjadi korban dari serangan biadab itu? Bagaimana pula dengan segelintir warga Amerika yang mensyukuri serangan itu sebagai “ujian bagi kesombongan Amerika”?
Dalam buku Catatan Pinggir, Goenawan Mohamad menyebut Guantanamo sebagai “tempat gelap sejenis nihilisme”. Di sini, di penjara Guantanamo, masa depan para tahanan tiba-tiba menjadi gelap.
Tak ada seorang pun yang bisa menyodorkan secercah cahaya kepada mereka untuk membuat masa depan kembali menjadi terang. Di titik ini, mereka bisa percaya Tuhan atau tidak sama sekali. Mereka juga bisa percaya bahwa sama sekali tak ada harapan atau bisa saja Tuhan mengirim malaikat berwujud pengacara hak asasi manusia bernama Nancy Hollander.
Baca Juga: Drama Korea yang Ratingnya Kecil tapi Menang Drama Terbaik Baeksang Arts Awards
Di Guantanamo, Mohamedou menjalani hukumannya dengan tabah. Awalnya dia syok, keimanannya terguncang hingga titik nadir sampai akhirnya dia pasrah dan berserah.
Dalam sebuah dialog yang tercantum di bagian paling atas tulisan ini, kita tahu Mohamedou menaruh harapan sepenuhnya pada Tuhan. Seseorang dengan nama alias Marseille, yang berbicara dengannya saat berada di luar bangunan penjara dengan pengamanan maksimum itu, meragukan gunanya untuk tetap menjalankan ibadah di tempat terkutuk seperti Guantanamo.
Namun Mohamedou tahu, Tuhan masih ada di sana, bersamanya, dan ribuan orang yang tak bersalah.
THE MAURITANIAN
Produser: Adam Ackland, Michael Bronner, Leah Clarke, Benedict Cumberbatch, Christine Holder, Mark Holder, Beatriz Levin, Lloyd Levin, Branwen Prestwood Smith
Sutradara: Kevin Macdonald
Penulis Skenario: M.B. Traven, Rory Haines, Sohrab Noshirvani
Pemain: Jodie Foster, Tahar Rahim, Benedict Cumberbatch
Ichwan Persada
Sutradara/produser/penulis skenario, pernah menjadi dosen di Universitas Padjajaran dan SAE Institute
(alv)