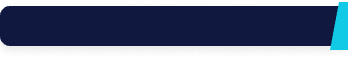Sastra Melayu Tionghoa, Asing di Negeri Sendiri
loading...

Sastra Melayu Tionghoa memakai bahasa yang dianggap rendah dibanding melayu tinggi yang jadi cikal bakal bahasa Indonesia. Foto/epnri.indonesiaheritage.org
A
A
A
JAKARTA - Sastra Melayu Tionghoa sempat membuat pusing Balai Pustaka, karena bahasanya dinilai rendah dan tidak menggambarkan citra baik Belanda.
"Sinar mata-hari kapan waktoe sedeng gilang-goemilang,
Antero boeroeng samboet dengen penoeh rasa girang,
Tapi itoe kegirangan gampang beroebah dan tenggelem,
Bila di sabelah koelon mata-hari pergi boeat silem"
Kapan Sampe Di Poetjaknja (1930) ditulis oleh Dahlia (Tan Lam Nio).
Potongan syair di atas mungkin terasa asing di mata pembaca Indonesia sekarang. Dari segi bahasa sudah terlihat dengan jelas bahwa potongan syair tersebut menggunakan ejaan lama. Ejaan yang sudah lama sekali kita tinggalkan.
Potongan tulisan tersebut merupakan novel yang dikarang oleh Tan Lam Nio atau yang dikenal dengan nama pena Dahlia. Ia merupakan seorang penyair peranakan Tionghoa dan menjadi salah satu sastrawan dalam kancah Kesusastraan Melayu-Tionghoa.
![Sastra Melayu Tionghoa, Asing di Negeri Sendiri]()
Foto: epnri.indonesiaheritage.org
Dahlia merupakan seorang penulis yang produktif. Sejak pertama menerbitkan bukunya pada 1931, dalam waktu tiga tahun saja, setidaknya dia menerbitkan lima buah roman dan beberapa cerita pendek dan syair, juga puisi.
Dalam karangannya, Dahlia menuliskan dan menyarikan cerita-cerita kehidupannya. Dalam karyanya itu dia juga membahas mengenai dinamika sosial dan politik. ( )
Dalam buku "Kesusastraan Melayu Tionghoa Jilid 1" terbitan Kepustakaan Populer Gramedia tahun 2000, yang disebut peranakan Tionghoa adalah mereka yang merupakan hasil kawin campur antara orang-orang Tionghoa dan masyarakat setempat.
Karya sastra Melayu Tionghoa diperkirakan muncul pada abad ke-19 dan populer pada abad ke-20. Sastra Melayu Tionghoa menurut Nio Joe Lan telah berakhir pada 1962.
Dalam "Kesusastraan Melayu Tionghoa Jilid 1" terbitan Kepustakaan Populer Gramedia, dia mengatakan bahwa tidak ada lagi tulisan peranakan Tionghoa yang menggunakan bahasa lisan sehari-hari.
Ia juga menambahkan bahwa menurut hukum Indonesia tidak ada lagi kaum peranakan, karena masyarakat keturunan Tionghoa tersebut telah menjadi bangsa Indonesia.
![Sastra Melayu Tionghoa, Asing di Negeri Sendiri]()
Foto: epnri.indonesiaheritage.org
Kesusastraan Melayu-Tionghoa merupakan karya tulisan dari peranakan Tionghoa yang menggunakan bahasa Melayu rendah atau bahasa Melayu Pasar.
Dalam karya sastra Melayu-Tionghoa, mereka menuliskan bahasa percakapan ke dalam karyanya. Bahasa Melayu rendah juga dapat diartikan sebagai bahasa yang mudah dimengerti dan menjadi bahasa sebagian besar penduduk Hindia Belanda.
Istilah bahasa Melayu Rendah diperkenalkan oleh pemerintah kolonial untuk membedakan dengan bahasa Melayu Tinggi, bahasa Melayu yang lebih baku dan terpandang.
Karya-karya dalam kesusastraan Melayu-Tionghoa biasanya merupakan saduran atau terjemahan karya sastra berbahasa China, saduran atau terjrmahan novel Barat, atau hasil karya si penulis itu sendiri.
Di luar dari karya terjemahan atau saduran, biasanya penulis mengangkat tema mengenai kondisi sosial masyarakat. Mengenai keadaan ekonomi terdapat beberapa novel yang menggambarkan tema tersebut misalkan "Berdjoeang" (1934) yang ditulis oleh Liem Khing Hoo dan "Masjarakat" (1940) yang ditulis oleh Than Sioe Tjhay.
Dalam bagian pengantar buku "Sastra Cina Peranakan dalam Bahasa Melayu" karya Claudines Salmon dikatakan bahwa sastra kaum peranakan ini pernah membuat pusing Balai Pustaka pada tahun 1930-an. ( )
![Sastra Melayu Tionghoa, Asing di Negeri Sendiri]()
Foto: epnri.indonesiaheritage.org
Karya-karya kaum peranakan Tionghoa ini dianggap sebagai bacaan liar oleh Balai Pustaka saat itu. Balai pustaka dengan kewenanangannya menganggap karya ini bermutu rendah karena tidak menggunakan bahasa Melayu tinggi dan baku seperti yang Balai pustaka gunakan.
Juga, kandungan dari karya sastra Melayu Tionghoa ini tidak menggambarkan citra baik Belanda seperti yang Balai Pustaka bingkai dalam buku-buku terbitannya.
Tempat yang tidak setara yang diberikan dalam sejarah perkembangan sastra Indonesia kepada sastra MelayuTionghoa karena dahulu penulis keturunan Tionghoa belum dianggap sebagai bagian masyarakat Indonesia.
Penulis keturunan Tionghoa tersebut hanya dianggap sebagai kalangan perantau. Alasan lain adalah penggunaan bahasa dalam karya sastra Melayu ionghoa adalah bahasa Melayu pasar dan bukan bahasa Melayu Tinggi. Melayu Tinggi dianggap sebagai cikal bakal Bahasa Indonesia modern saat ini.
Terlepas dari anggapan itu, karya-karya sastra Melayu Tionghoa sangat dekat dengan rakyat kebanyakan. Kemudahan memperoleh karya tersebut dan memahami karya tersebut adalah dampak yang dirasakan masyarakat secara luas.
Karya-karya sastra Melayu Tionghoa memberi dampak dari segi pengetahuan dan hiburan bagi masyarakat zaman tersebut. Sudah sepatutnya keberadaan sastra Melayu Tionghoa dianggap pentingnya dalam perkembangan sastra Indonesia.
Mungkin sudah saatnya kesusastraan Melayu Tionghoa diakui sebagai saudara kandung dalam keluarga kesusastraan Indonesia, dan bukannya dianggap sebagai saudara tiri. ( )
Putri Melina Febrianti
Kontributor GenSINDO
Universitas Indonesia
Instagram: @putri.melinaf
"Sinar mata-hari kapan waktoe sedeng gilang-goemilang,
Antero boeroeng samboet dengen penoeh rasa girang,
Tapi itoe kegirangan gampang beroebah dan tenggelem,
Bila di sabelah koelon mata-hari pergi boeat silem"
Kapan Sampe Di Poetjaknja (1930) ditulis oleh Dahlia (Tan Lam Nio).
Potongan syair di atas mungkin terasa asing di mata pembaca Indonesia sekarang. Dari segi bahasa sudah terlihat dengan jelas bahwa potongan syair tersebut menggunakan ejaan lama. Ejaan yang sudah lama sekali kita tinggalkan.
Potongan tulisan tersebut merupakan novel yang dikarang oleh Tan Lam Nio atau yang dikenal dengan nama pena Dahlia. Ia merupakan seorang penyair peranakan Tionghoa dan menjadi salah satu sastrawan dalam kancah Kesusastraan Melayu-Tionghoa.

Foto: epnri.indonesiaheritage.org
Dahlia merupakan seorang penulis yang produktif. Sejak pertama menerbitkan bukunya pada 1931, dalam waktu tiga tahun saja, setidaknya dia menerbitkan lima buah roman dan beberapa cerita pendek dan syair, juga puisi.
Dalam karangannya, Dahlia menuliskan dan menyarikan cerita-cerita kehidupannya. Dalam karyanya itu dia juga membahas mengenai dinamika sosial dan politik. ( )
Dalam buku "Kesusastraan Melayu Tionghoa Jilid 1" terbitan Kepustakaan Populer Gramedia tahun 2000, yang disebut peranakan Tionghoa adalah mereka yang merupakan hasil kawin campur antara orang-orang Tionghoa dan masyarakat setempat.
Karya sastra Melayu Tionghoa diperkirakan muncul pada abad ke-19 dan populer pada abad ke-20. Sastra Melayu Tionghoa menurut Nio Joe Lan telah berakhir pada 1962.
Dalam "Kesusastraan Melayu Tionghoa Jilid 1" terbitan Kepustakaan Populer Gramedia, dia mengatakan bahwa tidak ada lagi tulisan peranakan Tionghoa yang menggunakan bahasa lisan sehari-hari.
Ia juga menambahkan bahwa menurut hukum Indonesia tidak ada lagi kaum peranakan, karena masyarakat keturunan Tionghoa tersebut telah menjadi bangsa Indonesia.

Foto: epnri.indonesiaheritage.org
Kesusastraan Melayu-Tionghoa merupakan karya tulisan dari peranakan Tionghoa yang menggunakan bahasa Melayu rendah atau bahasa Melayu Pasar.
Dalam karya sastra Melayu-Tionghoa, mereka menuliskan bahasa percakapan ke dalam karyanya. Bahasa Melayu rendah juga dapat diartikan sebagai bahasa yang mudah dimengerti dan menjadi bahasa sebagian besar penduduk Hindia Belanda.
Istilah bahasa Melayu Rendah diperkenalkan oleh pemerintah kolonial untuk membedakan dengan bahasa Melayu Tinggi, bahasa Melayu yang lebih baku dan terpandang.
Karya-karya dalam kesusastraan Melayu-Tionghoa biasanya merupakan saduran atau terjemahan karya sastra berbahasa China, saduran atau terjrmahan novel Barat, atau hasil karya si penulis itu sendiri.
Di luar dari karya terjemahan atau saduran, biasanya penulis mengangkat tema mengenai kondisi sosial masyarakat. Mengenai keadaan ekonomi terdapat beberapa novel yang menggambarkan tema tersebut misalkan "Berdjoeang" (1934) yang ditulis oleh Liem Khing Hoo dan "Masjarakat" (1940) yang ditulis oleh Than Sioe Tjhay.
Dalam bagian pengantar buku "Sastra Cina Peranakan dalam Bahasa Melayu" karya Claudines Salmon dikatakan bahwa sastra kaum peranakan ini pernah membuat pusing Balai Pustaka pada tahun 1930-an. ( )

Foto: epnri.indonesiaheritage.org
Karya-karya kaum peranakan Tionghoa ini dianggap sebagai bacaan liar oleh Balai Pustaka saat itu. Balai pustaka dengan kewenanangannya menganggap karya ini bermutu rendah karena tidak menggunakan bahasa Melayu tinggi dan baku seperti yang Balai pustaka gunakan.
Juga, kandungan dari karya sastra Melayu Tionghoa ini tidak menggambarkan citra baik Belanda seperti yang Balai Pustaka bingkai dalam buku-buku terbitannya.
Tempat yang tidak setara yang diberikan dalam sejarah perkembangan sastra Indonesia kepada sastra MelayuTionghoa karena dahulu penulis keturunan Tionghoa belum dianggap sebagai bagian masyarakat Indonesia.
Penulis keturunan Tionghoa tersebut hanya dianggap sebagai kalangan perantau. Alasan lain adalah penggunaan bahasa dalam karya sastra Melayu ionghoa adalah bahasa Melayu pasar dan bukan bahasa Melayu Tinggi. Melayu Tinggi dianggap sebagai cikal bakal Bahasa Indonesia modern saat ini.
Terlepas dari anggapan itu, karya-karya sastra Melayu Tionghoa sangat dekat dengan rakyat kebanyakan. Kemudahan memperoleh karya tersebut dan memahami karya tersebut adalah dampak yang dirasakan masyarakat secara luas.
Karya-karya sastra Melayu Tionghoa memberi dampak dari segi pengetahuan dan hiburan bagi masyarakat zaman tersebut. Sudah sepatutnya keberadaan sastra Melayu Tionghoa dianggap pentingnya dalam perkembangan sastra Indonesia.
Mungkin sudah saatnya kesusastraan Melayu Tionghoa diakui sebagai saudara kandung dalam keluarga kesusastraan Indonesia, dan bukannya dianggap sebagai saudara tiri. ( )
Putri Melina Febrianti
Kontributor GenSINDO
Universitas Indonesia
Instagram: @putri.melinaf
(it)