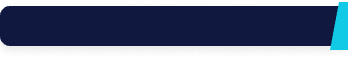CERMIN: Barbie, Proust, Patriarki, dan Eksistensialisme
loading...

Film Barbie banyak berbicara tentang budaya patriarki yang memandang perempuan dalam pengkotak-kotakan. Foto/Warner Bros
A
A
A
JAKARTA - “Sebuah imaji yang ditawarkan kepada kita membawa serta, dalam satu saat yang tunggal, sensasi yang berlipat ganda dan bermacam ragam” (Marcel Proust).
Saya tidak tahu apa yang saya rasakan setelah menonton film Barbieselama 114 menit. Saya tidak bisa menjelaskannya dalam sebuah kalimat yang bisa dipahami dengan sederhana. Hingga ucapan dari Proust ini muncul dan mengingatkan saya bahwa itulah yang saya rasakan ketika menyaksikan sebuah dunia rekaan Greta Gerwig yang luar biasa.
Saya menyaksikan Barbiedi bioskop seminggu setelah rilis perdananya. Jadi saya sudah pasti diterpa begitu banyak kritik, resensi hingga bocoran apa yang terjadi dalam film tersebut. Tapi saya selalu percaya bahwa saya bisa menilai sendiri atas apa yang saya tonton dan tak akan terpengaruh dengan kritik atau resensi mana pun.
Saya sudah menyukai karya-karya Greta Gerwig sejak menyaksikan Lady Bird(2017] dan Little Women (2019). Tapi saya tak pernah mempersiapkan apa pun sebelum menyaksikan karya paling mutakhirnya, Barbie. Dan yang terjadi adalah sensasi demi sensasi yang tak henti-hentinya saya saksikan sepanjang durasi filmnya.
![CERMIN: Barbie, Proust, Patriarki, dan Eksistensialisme]()
Foto: Warner Bros
Tak pernah sedikit pun terbayangkan oleh saya bahwa Barbie, sosok boneka paling terkenal sedunia yang juga diserang karena mencitrakan perempuan dengan standar kecantikan yang sulit digapai, akan menjadi pintu bagi Greta untuk memberi semacam kuliah filsafat dan sosiokultural yang asyik selama hampir dua jam. Tapi Greta, juga pasangannya, sesama sutradara sekaligus penulis, Noah Baumbach, bisa melakukannya seakan-akan ini adalah hal termudah di dunia.
Awalnya kita akan bertemu Barbie (diperankan dengan mulus oleh Margot Robbie) dengan penampilan serbasempurna dan hidup di dunianya yang sempurna. Segalanya berjalan semestinya, meski berupa repetisi demi repetisi yang terjadi setiap hari.
Kita juga bertemu dengan Ken (dengan penampilan dari Ryan Gosling yang layak mendapat nomine Oscar) yang sejatinya memang diciptakan sekedar untuk menemani Barbie. Dunia Barbie adalah dunia para perempuan dan laki-laki sekadar pelengkap. Sampai di sini kita mulai paham Greta akan membawa kita ke mana.
Hingga di sebuah hari yang biasa, Barbie bertemu dengan situasi yang tak biasa. Ia memikirkan kematian. Sebuah boneka dengan standar kesempurnaannya memikirkan kematian? Well, hanya Greta yang bisa melakukannya dan isu soal kematian, juga tentu saja eksistensialisme, mulai berkelindan dengan menarik ke dalam cerita.
![CERMIN: Barbie, Proust, Patriarki, dan Eksistensialisme]()
Foto: Warner Bros
Barbie tahu bahwa apa yang ia rasakan kemungkinan besar dirasakan oleh si pemiliknya. Ia tahu soal cerita ini dari apa yang pernah menimpa Barbie Aneh. Barbie tahu apa yang seharusnya ia lakukan. Ia harus melakukan perjalanan dari Dunia Barbie ke Dunia Nyata.
Seperti kata Proust, perjalanan dari suatu penemuan bukan dengan mencari pemandangan baru, tetapi dengan memiliki ‘mata baru, Barbie pun melihat apa yang sebenarnya terjadi di dunia nyata.
Berbeda dengan Barbie, Ken yang biasanya jadi pelengkap justru menemukan kenyataan bahwa perjalanannya kali ini membawanya untuk memahami soal patriarki. Greta menggunakan perspektifnya sebagai perempuan untuk berbicara soal male gaze ini dengan sangat pedas, bahkan mungkin bisa membuat sebagian pria terbatuk-batuk ketika mencoba menelannya.
Kritikus Christian Toto bahkan menganggap Barbiesebagai “Atwo hour wake-a-thon brimming with feminist lectures and nuclear-level weapon rage against men”.
Barbie dan Ken mengalami pengalaman yang berbeda di dunia nyata dan membuat Dunia Barbie berantakan ketika mereka kembali. Untungnya memang ada Gloria, satu-satunya pekerja perempuan di Mattel, perusahaan yang memproduksi boneka Barbie.
Dalam pidatonya yang panjang dan sekaligus menggugah, Gloria menyentil kita, utamanya pria seperti saya, yang selalu melihat perempuan dalam berbagai standar yang kerap kali mengungkung mereka.
![CERMIN: Barbie, Proust, Patriarki, dan Eksistensialisme]()
Foto: Warner Bros
Apa yang dibicarakan Gloria bisa jadi akan beresonansi hingga seabad mendatang terkait eksistensialisme perempuan. Bisa jadi ia akan dikutip banyak jurnal hingga tulisan panjang nan serius karena keberhasilannya menyadarkan kita bahwa selama ini hampir selalu kita memasukkan perempuan ke dalam kotak tertentu.
Kita memberi mereka beragam label, memberi mereka beragam batasan, yang pada batas tertentu akan terasa sangat menyesakkan bagi mereka. Terutama ketika kita selalu memberi standar tertentu pada perempuan yang selalu menyulitkan mereka.
Saya tidak tahu apa yang saya rasakan setelah menonton film Barbieselama 114 menit. Saya tidak bisa menjelaskannya dalam sebuah kalimat yang bisa dipahami dengan sederhana. Hingga ucapan dari Proust ini muncul dan mengingatkan saya bahwa itulah yang saya rasakan ketika menyaksikan sebuah dunia rekaan Greta Gerwig yang luar biasa.
Saya menyaksikan Barbiedi bioskop seminggu setelah rilis perdananya. Jadi saya sudah pasti diterpa begitu banyak kritik, resensi hingga bocoran apa yang terjadi dalam film tersebut. Tapi saya selalu percaya bahwa saya bisa menilai sendiri atas apa yang saya tonton dan tak akan terpengaruh dengan kritik atau resensi mana pun.
Saya sudah menyukai karya-karya Greta Gerwig sejak menyaksikan Lady Bird(2017] dan Little Women (2019). Tapi saya tak pernah mempersiapkan apa pun sebelum menyaksikan karya paling mutakhirnya, Barbie. Dan yang terjadi adalah sensasi demi sensasi yang tak henti-hentinya saya saksikan sepanjang durasi filmnya.

Foto: Warner Bros
Tak pernah sedikit pun terbayangkan oleh saya bahwa Barbie, sosok boneka paling terkenal sedunia yang juga diserang karena mencitrakan perempuan dengan standar kecantikan yang sulit digapai, akan menjadi pintu bagi Greta untuk memberi semacam kuliah filsafat dan sosiokultural yang asyik selama hampir dua jam. Tapi Greta, juga pasangannya, sesama sutradara sekaligus penulis, Noah Baumbach, bisa melakukannya seakan-akan ini adalah hal termudah di dunia.
Awalnya kita akan bertemu Barbie (diperankan dengan mulus oleh Margot Robbie) dengan penampilan serbasempurna dan hidup di dunianya yang sempurna. Segalanya berjalan semestinya, meski berupa repetisi demi repetisi yang terjadi setiap hari.
Kita juga bertemu dengan Ken (dengan penampilan dari Ryan Gosling yang layak mendapat nomine Oscar) yang sejatinya memang diciptakan sekedar untuk menemani Barbie. Dunia Barbie adalah dunia para perempuan dan laki-laki sekadar pelengkap. Sampai di sini kita mulai paham Greta akan membawa kita ke mana.
Hingga di sebuah hari yang biasa, Barbie bertemu dengan situasi yang tak biasa. Ia memikirkan kematian. Sebuah boneka dengan standar kesempurnaannya memikirkan kematian? Well, hanya Greta yang bisa melakukannya dan isu soal kematian, juga tentu saja eksistensialisme, mulai berkelindan dengan menarik ke dalam cerita.

Foto: Warner Bros
Barbie tahu bahwa apa yang ia rasakan kemungkinan besar dirasakan oleh si pemiliknya. Ia tahu soal cerita ini dari apa yang pernah menimpa Barbie Aneh. Barbie tahu apa yang seharusnya ia lakukan. Ia harus melakukan perjalanan dari Dunia Barbie ke Dunia Nyata.
Seperti kata Proust, perjalanan dari suatu penemuan bukan dengan mencari pemandangan baru, tetapi dengan memiliki ‘mata baru, Barbie pun melihat apa yang sebenarnya terjadi di dunia nyata.
Berbeda dengan Barbie, Ken yang biasanya jadi pelengkap justru menemukan kenyataan bahwa perjalanannya kali ini membawanya untuk memahami soal patriarki. Greta menggunakan perspektifnya sebagai perempuan untuk berbicara soal male gaze ini dengan sangat pedas, bahkan mungkin bisa membuat sebagian pria terbatuk-batuk ketika mencoba menelannya.
Kritikus Christian Toto bahkan menganggap Barbiesebagai “Atwo hour wake-a-thon brimming with feminist lectures and nuclear-level weapon rage against men”.
Barbie dan Ken mengalami pengalaman yang berbeda di dunia nyata dan membuat Dunia Barbie berantakan ketika mereka kembali. Untungnya memang ada Gloria, satu-satunya pekerja perempuan di Mattel, perusahaan yang memproduksi boneka Barbie.
Dalam pidatonya yang panjang dan sekaligus menggugah, Gloria menyentil kita, utamanya pria seperti saya, yang selalu melihat perempuan dalam berbagai standar yang kerap kali mengungkung mereka.

Foto: Warner Bros
Apa yang dibicarakan Gloria bisa jadi akan beresonansi hingga seabad mendatang terkait eksistensialisme perempuan. Bisa jadi ia akan dikutip banyak jurnal hingga tulisan panjang nan serius karena keberhasilannya menyadarkan kita bahwa selama ini hampir selalu kita memasukkan perempuan ke dalam kotak tertentu.
Kita memberi mereka beragam label, memberi mereka beragam batasan, yang pada batas tertentu akan terasa sangat menyesakkan bagi mereka. Terutama ketika kita selalu memberi standar tertentu pada perempuan yang selalu menyulitkan mereka.