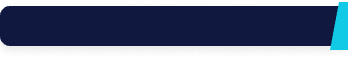CERMIN: John Green dan Keberaniannya Membuka Diri soal Isu Kesehatan Mental
loading...

Film Turtles All the Way Down mengisahkan seorang remaja dengan isu kesehatan mental yang takut berciuman. Foto/HBO Go
A
A
A
JAKARTA - Tahun 2021. Kala seantero dunia sedang dirundung pandemi, saya mengalami fase yang paling tak pernah terpikirkan dalam hidup saya: mengalami depresi.
Saya merasa sudah pernah mengalami segala hal buruk yang pernah diterima oleh seorang manusia. Pada usia 16 tahun, ibu saya meninggal mendadak karena kecelakaan mobil.
Pada usia 27 tahun, adik saya meninggal karena dicengkeram AIDS. Saya akhirnya pun selalu berpikir bahwa saya tak akan melewati usia 40 tahun.
Namun bukan itu semua yang membuat saya depresi. Pertaruhan besar atas sebuah rencana bisnis yang nyaris gagal total membuyarkan segalanya.
Saya merasa seluruh dunia gelap, saya merasa jatuh ke lubang yang sangat dalam dan tak seorang pun mengulurkan tangan untuk membawa saya kembali naik ke atas.
Pada 2022, saya membaca pengakuan terbuka dari seorang penulis yang saya kagumi soal pengalamannya ingin bunuh diri saat pandemi yang menghancurkan finansialnya. Perlahan saya tahu bahwa banyak orang yang mengalami hal yang sama, dan seperti John Green, saya tak ingin lagi menyembunyikannya. Saya ingin membicarakannya secara terbuka.
Seperti John, saya menginjeksikan secuil pengalaman itu dalam skenario miniseri yang lantas dinovelkan terlebih dahulu oleh Eunike Hanny berjudul Klub Bunuh Diri. Sebuah kisah tentang para pemberani yang mengakui secara lantang terkait masalah yang tak bisa lagi mereka tanggulangi dan mengulurkan tangannya untuk digenggam oleh mereka yang peduli.
Sementara John ingin menjaga jarak antara kesulitan yang dihadapinya dan naskah novel yang ditulisnya, maka komprominya mewujud ke dalam bentuk karakter utama, seorang remaja perempuan bernama Aza yang mengidap Obsessive Compulsive Disorder (OCD).
![CERMIN: John Green dan Keberaniannya Membuka Diri soal Isu Kesehatan Mental]()
Foto: HBO Go
Aza punya kekhawatiran berlebihan terhadap bakteri yang menginvasi seluruh pemikirannya. Ia membiarkan pemikiran itu sering kali menyetir bagian-bagian paling penting dalam hidupnya termasuk saat seharusnya ia menikmati ciuman pertamanya.
Dalam film yang tayang di HBO Go ini, sutradara Hannah Marks membiarkan kita mengintip ketakutan demi ketakutan yang silih berganti menghinggapi Aza melalui voice-over. Meski sering kali efektif, terkadang voice-over itu terasa terlalu berlebihan dan terasa supercerewet untuk sebuah adegan yang sesungguhnya tak memerlukannya.
Pendekatan voice-over ini memang berisiko besar. Untungnya memang Hannah berhasil menghindari kekacauan demi kekacauan yang mungkin datang dari pendekatan ini.
Kita pun mendengar bagaimana kekhawatiran Aza ini terasa sangat menganggu hidupnya. Jika seorang remaja perempuan sepertinya menginginkan ciuman pertama yang sempurna, Aza justru terkesan takut melakukannya atas sebuah hal yang belum tentu terjadi.
Aza lalu menyemburkan kekhawatirannya kepada psikiaternya dengan seruan, “How can I have a boyfriend if I hate the idea of kissing him?”. Termasuk pikiran-pikiran yang terus bergejolak dalam kepalanya yang memuncratkan ide seperti, “You’ll get his bacteria in your mouth. His bacteria will make you sick”, tentu saja bisa dengan mudah membuat kehidupan Aza begitu rapuhnya.
![CERMIN: John Green dan Keberaniannya Membuka Diri soal Isu Kesehatan Mental]()
Foto: HBO Go
Untungnya memang Aza punya Daisy, sahabat sejati yang selalu berada di sisinya. Berusaha memahami sisi-sisi terburuknya yang nyaris tak pernah diperlihatkannya kepada siapa pun.
Daisy berusaha mengerti bahwa sering kali Aza dan masalahnya mengambil alih semesta persahabatan mereka dan membuat Aza terus menerus menjadi pemeran utamanya. John begitu cerdik menempatkan dua karakter yang terkesan bertolak belakang, tapi justru karena ketaksamaan keduanya lah yang membuat mereka lebih mudah memahami satu sama lain.
Membicarakan isu kesehatan mental pada hari-hari ini masih tak mudah. Masih banyak yang menghindarinya, masih banyak yang ingin membicarakannya sekadar bisik-bisik.
Padahal sejumlah survei sudah memperlihatkan betapa rentannya generasi muda di negeri ini dengan isu tersebut. Keberanian John dan penulis-penulis lainnya untuk membicarakannya secara terbuka adalah sebuah keberanian yang patut diberi keplokan meriah.
![CERMIN: John Green dan Keberaniannya Membuka Diri soal Isu Kesehatan Mental]()
Foto: HBO Go
Kita tentu saja terus berharap bahwa pada tahun-tahun mendatang, kita semakin memberi tempat, hati, dan empati untuk isu ini. Bahwa isu ini sama pentingnya dengan pendidikan yang masih belum merata, jumlah penduduk miskin yang semakin bertambah, dan akses masyarakat terhadap kesehatan yang masih terbilang rendah.
Saya membayangkan tiga karakter utama dalam novel Klub Bunuh Diri bertemu dengan dua karakter utama dalam Turtles All the Way Down. Rama, Vino, dan Sinta akhirnya bertemu dengan Aza dan Daisy. mereka membicarakan masalah-masalah yang mereka alami.
Mereka secara terbuka mengakui bahwa mereka butuh pertolongan, dan mereka pun paham bahwa masih cukup banyak orang yang akan mengulurkan tangan saat mereka terjatuh ke dalam lubang yang dalam. Bahwa hidup tak akan jadi hidup ketika manusia yang mengalaminya tak ditempa masalah demi masalah.
Namun masalah akan berlalu, penderitaan akan berakhir. Kita mengamini apa yang diyakini John Green, “The only way out of labyrinth of suffering is to forgive”.
Turtles All the Way Down
Produser: Marty Bowen, Wyck Godfrey, Isaac Klausner
Penulis Skenario: Elizabeth Berger, Isaac Aptaker
Sutradara: Hannah Marks
Pemain: Isabella Merced, Cree, Felix Mallard
Ichwan Persada
Sutradara/produser/penulis skenario, pernah menjadi dosen di Universitas Padjajaran dan SAE Institute, bisa dikontak via Instagram @ichwanpersada
Saya merasa sudah pernah mengalami segala hal buruk yang pernah diterima oleh seorang manusia. Pada usia 16 tahun, ibu saya meninggal mendadak karena kecelakaan mobil.
Pada usia 27 tahun, adik saya meninggal karena dicengkeram AIDS. Saya akhirnya pun selalu berpikir bahwa saya tak akan melewati usia 40 tahun.
Namun bukan itu semua yang membuat saya depresi. Pertaruhan besar atas sebuah rencana bisnis yang nyaris gagal total membuyarkan segalanya.
Saya merasa seluruh dunia gelap, saya merasa jatuh ke lubang yang sangat dalam dan tak seorang pun mengulurkan tangan untuk membawa saya kembali naik ke atas.
Pada 2022, saya membaca pengakuan terbuka dari seorang penulis yang saya kagumi soal pengalamannya ingin bunuh diri saat pandemi yang menghancurkan finansialnya. Perlahan saya tahu bahwa banyak orang yang mengalami hal yang sama, dan seperti John Green, saya tak ingin lagi menyembunyikannya. Saya ingin membicarakannya secara terbuka.
Seperti John, saya menginjeksikan secuil pengalaman itu dalam skenario miniseri yang lantas dinovelkan terlebih dahulu oleh Eunike Hanny berjudul Klub Bunuh Diri. Sebuah kisah tentang para pemberani yang mengakui secara lantang terkait masalah yang tak bisa lagi mereka tanggulangi dan mengulurkan tangannya untuk digenggam oleh mereka yang peduli.
Sementara John ingin menjaga jarak antara kesulitan yang dihadapinya dan naskah novel yang ditulisnya, maka komprominya mewujud ke dalam bentuk karakter utama, seorang remaja perempuan bernama Aza yang mengidap Obsessive Compulsive Disorder (OCD).

Foto: HBO Go
Aza punya kekhawatiran berlebihan terhadap bakteri yang menginvasi seluruh pemikirannya. Ia membiarkan pemikiran itu sering kali menyetir bagian-bagian paling penting dalam hidupnya termasuk saat seharusnya ia menikmati ciuman pertamanya.
Dalam film yang tayang di HBO Go ini, sutradara Hannah Marks membiarkan kita mengintip ketakutan demi ketakutan yang silih berganti menghinggapi Aza melalui voice-over. Meski sering kali efektif, terkadang voice-over itu terasa terlalu berlebihan dan terasa supercerewet untuk sebuah adegan yang sesungguhnya tak memerlukannya.
Pendekatan voice-over ini memang berisiko besar. Untungnya memang Hannah berhasil menghindari kekacauan demi kekacauan yang mungkin datang dari pendekatan ini.
Kita pun mendengar bagaimana kekhawatiran Aza ini terasa sangat menganggu hidupnya. Jika seorang remaja perempuan sepertinya menginginkan ciuman pertama yang sempurna, Aza justru terkesan takut melakukannya atas sebuah hal yang belum tentu terjadi.
Aza lalu menyemburkan kekhawatirannya kepada psikiaternya dengan seruan, “How can I have a boyfriend if I hate the idea of kissing him?”. Termasuk pikiran-pikiran yang terus bergejolak dalam kepalanya yang memuncratkan ide seperti, “You’ll get his bacteria in your mouth. His bacteria will make you sick”, tentu saja bisa dengan mudah membuat kehidupan Aza begitu rapuhnya.

Foto: HBO Go
Untungnya memang Aza punya Daisy, sahabat sejati yang selalu berada di sisinya. Berusaha memahami sisi-sisi terburuknya yang nyaris tak pernah diperlihatkannya kepada siapa pun.
Daisy berusaha mengerti bahwa sering kali Aza dan masalahnya mengambil alih semesta persahabatan mereka dan membuat Aza terus menerus menjadi pemeran utamanya. John begitu cerdik menempatkan dua karakter yang terkesan bertolak belakang, tapi justru karena ketaksamaan keduanya lah yang membuat mereka lebih mudah memahami satu sama lain.
Membicarakan isu kesehatan mental pada hari-hari ini masih tak mudah. Masih banyak yang menghindarinya, masih banyak yang ingin membicarakannya sekadar bisik-bisik.
Padahal sejumlah survei sudah memperlihatkan betapa rentannya generasi muda di negeri ini dengan isu tersebut. Keberanian John dan penulis-penulis lainnya untuk membicarakannya secara terbuka adalah sebuah keberanian yang patut diberi keplokan meriah.

Foto: HBO Go
Kita tentu saja terus berharap bahwa pada tahun-tahun mendatang, kita semakin memberi tempat, hati, dan empati untuk isu ini. Bahwa isu ini sama pentingnya dengan pendidikan yang masih belum merata, jumlah penduduk miskin yang semakin bertambah, dan akses masyarakat terhadap kesehatan yang masih terbilang rendah.
Saya membayangkan tiga karakter utama dalam novel Klub Bunuh Diri bertemu dengan dua karakter utama dalam Turtles All the Way Down. Rama, Vino, dan Sinta akhirnya bertemu dengan Aza dan Daisy. mereka membicarakan masalah-masalah yang mereka alami.
Mereka secara terbuka mengakui bahwa mereka butuh pertolongan, dan mereka pun paham bahwa masih cukup banyak orang yang akan mengulurkan tangan saat mereka terjatuh ke dalam lubang yang dalam. Bahwa hidup tak akan jadi hidup ketika manusia yang mengalaminya tak ditempa masalah demi masalah.
Namun masalah akan berlalu, penderitaan akan berakhir. Kita mengamini apa yang diyakini John Green, “The only way out of labyrinth of suffering is to forgive”.
Turtles All the Way Down
Produser: Marty Bowen, Wyck Godfrey, Isaac Klausner
Penulis Skenario: Elizabeth Berger, Isaac Aptaker
Sutradara: Hannah Marks
Pemain: Isabella Merced, Cree, Felix Mallard
Ichwan Persada
Sutradara/produser/penulis skenario, pernah menjadi dosen di Universitas Padjajaran dan SAE Institute, bisa dikontak via Instagram @ichwanpersada
(ita)