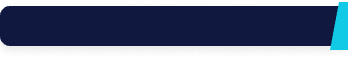CERMIN: Dalam Hidup Kita Perlu Menang Sekali Saja
loading...

Film China YOLO menggambarkan transformasi perempuan pemalas bermental pecundang menjadi petinju mental pemenang. Foto/Shanghai Taopiaopiao Film and Television
A
A
A
JAKARTA - Tahun 2014. Jepang mendaftarkan film 100 Yen Love sebagai official entry untuk berkompetisi dengan film-film internasional terbaik dari seluruh dunia dalam ajang Academy Awards.
Dari sini pun kita tahu bahwa 100 Yen Love memang sebuah film yang istimewa. Sekaligus memperlihatkan perkembangan terkini dari sinema Asia saat film semakin berani mengetengahkan protagonis dengan kehidupan menyedihkan, tak punya harapan apa pun, dan dengan sebuah jalan kelak mereka mengubah drastis hidupnya.
Dalam 100 Yen Love, protagonis menyedihkan itu adalah Saito Ichiko, perempuan berusia 32 tahun yang tak punya tujuan apa pun dalam hidupnya, dan masih tinggal bersama orang tuanya. Hingga semesta memberinya kejutan dengan memperkenalkannya pada olahraga tinju yang akan mengubah drastis hidupnya setelahnya.
Dengan premis sedemikian menarik rasanya memang sulit untuk tak mengindahkan 100 Yen Love. Terlebih di tangan sutradara Take Masahiru.
Meski berjalan dengan tempo lambat (yang mungkin memang dibutuhkan oleh ceritanya), perlahan kita melihat bagaimana sinema juga bisa mencerahkan. Sebagaimana Saito, sebagian dari kita pun ingin melakukan perubahan dalam hidup kita, tapi bisa jadi terlalu takut untuk melakukannya.
![CERMIN: Dalam Hidup Kita Perlu Menang Sekali Saja]()
Foto: Shanghai Taopiaopiao Film and Television
Beberapa tahun setelahnya, sutradara perempuan sekaligus aktris China, Ling Jia, terkesan betul dengan cerita 100 Yen Love dan memutuskan untuk membuat ulang film tersebut. Tak sekadar membuat ulang, Ling Jia berupaya melakukan perbaikan sana-sini di departemen skenario dan terutama mendorong penceritaan ke titik yang lebih maksimal.
Sebagaimana kita yang jatuh hati pada perjuangan dan determinasi Ichiko, Ling Jia memutuskan untuk memainkan sendiri peran tersebut. Kini Ichiko berubah menjadi Le Ying, perempuan superpemalas yang hanya menjadi benalu dalam hidup kedua orang tuanya.
Semuanya berubah ketika pertengkaran terjadi antara Le Ying dan adiknya yang membuatnya memutuskan hengkang dari rumah.
Jika dibandingkan, 100Yen Love terasa berjalan dengan tempo lambat, sedangkan YOLO justru terasa berpanjang-panjang karena kukuh memperlihatkan segala detail yang dilalui Le Ying hingga akhirnya bertemu dengan dunia baru: tinju.
Begitu pun proses perjalanan Le Ying diceritakan dengan begitu bersemangat ,sehingga membuat kita menaruh harapan dan ekspektasi tertentu padanya.
Segala episode dalam perjalanan itu mulai dari Le Ying menjadi pelayan, tak sengaja bertemu pelatih tinju yang diam-diam dicintainya, lantas patah hati karenanya, kemudian memutuskan menyeriusi dunia tinju, membuat kita berempati padanya. Empati itu terutama didapatkan oleh Le Ying karena pemeranannya yang total.
![CERMIN: Dalam Hidup Kita Perlu Menang Sekali Saja]()
Foto: Shanghai Taopiaopiao Film and Television
Ia bertransformasi dengan mulus dan meyakinkan dari seorang perempuan pemalas, tambun, suka mengasihani diri sendiri, menjadi perempuan penuh tekad, mendorong dirinya berlatih habis-habisan dan sekali saja ingin menjadi pemenang dalam hidupnya. Le Ying yang dirundung sejak kecil karena penampilan fisiknya berharap tinju bisa memberikannya kemenangan yang sudah dinantikannya seumur hidupnya.
Namunkita tahu kemenangan hampir selalu tak mudah didapatkan. Apalagi menang di ring tinju. Le Ying bukan petinju profesional yang sudah berlatih bertahun-tahun, tapi determinasinya menaklukkan segala keraguan terhadapnya.
Perlahan empati kita sebagai penonton berubah menjadi respek kepadanya. Pada titik inilah YOLO berhasil merebut hati kita.
Dengan munculnya generasi baru penonton bioskop yang semakin mengapresiasi cerita-cerita orisinal, kita pun berharap rumah-rumah produksi besar memberi tempat pada cerita-cerita sejenis YOLO untuk tumbuh, berkembang, dan menemukan penontonnya di bioskop di Indonesia.
Mungkin kita sudah bosan dengan cerita-cerita yang memperlihatkan protagonis dengan segala kesempurnaannya, protagonis dengan kehidupan serba mudah di luar negeri, atau protagonis yang seperti tak mensyukuri hidupnya yang bergelimang privilege.
![CERMIN: Dalam Hidup Kita Perlu Menang Sekali Saja]()
Foto:Shanghai Taopiaopiao Film and Television
Dari sini pun kita tahu bahwa 100 Yen Love memang sebuah film yang istimewa. Sekaligus memperlihatkan perkembangan terkini dari sinema Asia saat film semakin berani mengetengahkan protagonis dengan kehidupan menyedihkan, tak punya harapan apa pun, dan dengan sebuah jalan kelak mereka mengubah drastis hidupnya.
Dalam 100 Yen Love, protagonis menyedihkan itu adalah Saito Ichiko, perempuan berusia 32 tahun yang tak punya tujuan apa pun dalam hidupnya, dan masih tinggal bersama orang tuanya. Hingga semesta memberinya kejutan dengan memperkenalkannya pada olahraga tinju yang akan mengubah drastis hidupnya setelahnya.
Dengan premis sedemikian menarik rasanya memang sulit untuk tak mengindahkan 100 Yen Love. Terlebih di tangan sutradara Take Masahiru.
Meski berjalan dengan tempo lambat (yang mungkin memang dibutuhkan oleh ceritanya), perlahan kita melihat bagaimana sinema juga bisa mencerahkan. Sebagaimana Saito, sebagian dari kita pun ingin melakukan perubahan dalam hidup kita, tapi bisa jadi terlalu takut untuk melakukannya.

Foto: Shanghai Taopiaopiao Film and Television
Beberapa tahun setelahnya, sutradara perempuan sekaligus aktris China, Ling Jia, terkesan betul dengan cerita 100 Yen Love dan memutuskan untuk membuat ulang film tersebut. Tak sekadar membuat ulang, Ling Jia berupaya melakukan perbaikan sana-sini di departemen skenario dan terutama mendorong penceritaan ke titik yang lebih maksimal.
Sebagaimana kita yang jatuh hati pada perjuangan dan determinasi Ichiko, Ling Jia memutuskan untuk memainkan sendiri peran tersebut. Kini Ichiko berubah menjadi Le Ying, perempuan superpemalas yang hanya menjadi benalu dalam hidup kedua orang tuanya.
Semuanya berubah ketika pertengkaran terjadi antara Le Ying dan adiknya yang membuatnya memutuskan hengkang dari rumah.
Jika dibandingkan, 100Yen Love terasa berjalan dengan tempo lambat, sedangkan YOLO justru terasa berpanjang-panjang karena kukuh memperlihatkan segala detail yang dilalui Le Ying hingga akhirnya bertemu dengan dunia baru: tinju.
Begitu pun proses perjalanan Le Ying diceritakan dengan begitu bersemangat ,sehingga membuat kita menaruh harapan dan ekspektasi tertentu padanya.
Segala episode dalam perjalanan itu mulai dari Le Ying menjadi pelayan, tak sengaja bertemu pelatih tinju yang diam-diam dicintainya, lantas patah hati karenanya, kemudian memutuskan menyeriusi dunia tinju, membuat kita berempati padanya. Empati itu terutama didapatkan oleh Le Ying karena pemeranannya yang total.

Foto: Shanghai Taopiaopiao Film and Television
Ia bertransformasi dengan mulus dan meyakinkan dari seorang perempuan pemalas, tambun, suka mengasihani diri sendiri, menjadi perempuan penuh tekad, mendorong dirinya berlatih habis-habisan dan sekali saja ingin menjadi pemenang dalam hidupnya. Le Ying yang dirundung sejak kecil karena penampilan fisiknya berharap tinju bisa memberikannya kemenangan yang sudah dinantikannya seumur hidupnya.
Namunkita tahu kemenangan hampir selalu tak mudah didapatkan. Apalagi menang di ring tinju. Le Ying bukan petinju profesional yang sudah berlatih bertahun-tahun, tapi determinasinya menaklukkan segala keraguan terhadapnya.
Perlahan empati kita sebagai penonton berubah menjadi respek kepadanya. Pada titik inilah YOLO berhasil merebut hati kita.
Dengan munculnya generasi baru penonton bioskop yang semakin mengapresiasi cerita-cerita orisinal, kita pun berharap rumah-rumah produksi besar memberi tempat pada cerita-cerita sejenis YOLO untuk tumbuh, berkembang, dan menemukan penontonnya di bioskop di Indonesia.
Mungkin kita sudah bosan dengan cerita-cerita yang memperlihatkan protagonis dengan segala kesempurnaannya, protagonis dengan kehidupan serba mudah di luar negeri, atau protagonis yang seperti tak mensyukuri hidupnya yang bergelimang privilege.

Foto:Shanghai Taopiaopiao Film and Television