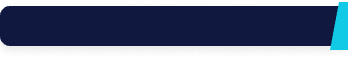CERMIN: Amerika Seharusnya Sudah Punya Presiden Perempuan sejak 1972
loading...

Film Shirley menampilkan politikus perempuan Afrika-Amerika pertama yang menjadi anggota kongres pada akhir 1960-an. Foto/Netflix
A
A
A
JAKARTA - Pada 23 Juli 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat mencopot Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia dan lantas mendudukkan Megawati sebagai perempuan pertama yang menduduki jabatan tertinggi di negeri ini.
Namunketika mencoba bertarung kembali dalam pemilihan presiden tahun 2004, Megawati kalah telak dari Susilo Bambang Yudhoyono.
Begitupun dalam soal kepresidenan, Indonesia melampaui yang sudah diupayakan Amerika sejak puluhan tahun silam. Ketika Shirley Chisholm terpilih sebagai perempuan Afrika-Amerika pertama yang menjadi anggota kongres, maka pintu-pintu mulai terbuka sedikit demi sedikit atas ide datangnya presiden perempuan.
Shirley menenun ide-ide itu sejak tahun 1972, 29 tahun sebelum Megawati mencatat sejarah di Indonesia.
Menyaksikan film Shirley yang tayang di Netflix sejatinya adalah menyaksikan bagaimana sejarah sedang coba dirakit. Meski kita semua tahu ujung cerita ini akan seperti apa, tapi sutradara John Ridley memberi ruang terutama bagi generasi muda untuk tahu bahwa perempuan-perempuan pendobrak seperti Shirley perlu diingat kembali hari-hari ini.
![CERMIN: Amerika Seharusnya Sudah Punya Presiden Perempuan sejak 1972]()
Foto: Netflix
Film dibuka dengan efektif memperlihatkan bagaimana Shirley terpilih dan membuat sejarah di kongres, juga bagaimana ia didukung sepenuhnya oleh sang suami, Conrad. Masuknya Shirley ke kongres juga menyalakan bara yang selama ini mendekam cukup lama di tubuhnya.
Ia tahu sebagai perempuan, sebagai keturunan Afrika-Amerika, sebagai minoritas, maka Shirley akan menempuh perjuangan hingga tiga kali lebih sulit dari yang dijalaninya koleganya, para laki-laki kulit putih.
Tapi ia sudah memperhitungkan semuanya dan terus menggemakan “give politics back to the people”, kembalikan politik kepada rakyat. Sebuah pemikiran yang penuh idealisme tapi mungkin pula bisa terdengar begitu utopis.
Mungkin memang hanya sosok pendobrak seperti Shirley yang bisa mendorong pemikiran seperti itu bisa diterima oleh lebih banyak kalangan.
Dalam skenario yang ditulis John, ruang dibuka lebar bagi kita untuk melihat bagaimana Shirley masuk ke arena politik, menyesuaikan diri, memahami lawan-lawan politiknya, bahkan nyaris tewas ditikam oleh seseorang di tengah kerumunan.
![CERMIN: Amerika Seharusnya Sudah Punya Presiden Perempuan sejak 1972]()
Foto: Netflix
Namun sayangnya skenario tak memberi ruang cukup luas bagi kita untuk mengenali bagaimana Shirley sesungguhnya, bagaimana ia mengenal politik, memutuskan masuk ke pertarungan tak seimbang, hanya untuk pada akhirnya dikalahkan dengan tak adil.
Ini jadi sulit bagi kita untuk bersimpati pada Shirley sebagai seorang perempuan. Bahkan sebagian bisa jadi membencinya ketika diperlihatkan betapa suami yang selalu mendukungnya pun bisa disalahkannya, ditentangnya habis-habisan, dan menguras rasa cinta di antara keduanya dengan cepat.
Kita pun sulit bersimpati pada Shirley sebagai seorang keturunan Afrika-Amerika tanpa pernah diperlihatkan secara jelas apa yang pernah dilakukannya untuk kaumnya. Bahkan sebagian bisa jadi membencinya ketika melihat bahkan kakaknya sendiri, Muriel, tak mendukung pencalonannya sebagai presiden yang dianggapnya hanya menyusahkan dirinya dan ibunya semata.
Kita sulit bersimpati karena Shirley lebih banyak digambarkan oleh John sebagai ikon, bukan sebagai manusia biasa. Kita tak pernah melihatnya menangis dalam gelap dan dalam diam menyikapi pertarungan habis-habisan yang harus dijalaninya.
Kita tak pernah diberi kesempatan melihat bagaimana ia mencoba bersiasat di tengah situasi keruh rumah tangganya. Shirley Chisholm dalam Shirley hanyalah seorang politikus perempuan ambisius yang idealis, bukan manusia biasa yang melihat masalah-masalah yang ada di masyarakat yang perlu dipecahkan segera dan bisa diupayakannya ketika ia menjadi presiden kelak.
![CERMIN: Amerika Seharusnya Sudah Punya Presiden Perempuan sejak 1972]()
Foto: Netflix
Sebagaimana Rustin yang juga bergerak dalam skema cerita yang sama dan dengan pendekatan yang mirip, Shirley juga mudah mencuri perhatian kita karena penampilan mengagumkan dari peraih Oscar, Regina King. Susah membayangkan jika Shirley Chisholm tak diperankan olehnya.
Namunketika mencoba bertarung kembali dalam pemilihan presiden tahun 2004, Megawati kalah telak dari Susilo Bambang Yudhoyono.
Begitupun dalam soal kepresidenan, Indonesia melampaui yang sudah diupayakan Amerika sejak puluhan tahun silam. Ketika Shirley Chisholm terpilih sebagai perempuan Afrika-Amerika pertama yang menjadi anggota kongres, maka pintu-pintu mulai terbuka sedikit demi sedikit atas ide datangnya presiden perempuan.
Shirley menenun ide-ide itu sejak tahun 1972, 29 tahun sebelum Megawati mencatat sejarah di Indonesia.
Menyaksikan film Shirley yang tayang di Netflix sejatinya adalah menyaksikan bagaimana sejarah sedang coba dirakit. Meski kita semua tahu ujung cerita ini akan seperti apa, tapi sutradara John Ridley memberi ruang terutama bagi generasi muda untuk tahu bahwa perempuan-perempuan pendobrak seperti Shirley perlu diingat kembali hari-hari ini.

Foto: Netflix
Film dibuka dengan efektif memperlihatkan bagaimana Shirley terpilih dan membuat sejarah di kongres, juga bagaimana ia didukung sepenuhnya oleh sang suami, Conrad. Masuknya Shirley ke kongres juga menyalakan bara yang selama ini mendekam cukup lama di tubuhnya.
Ia tahu sebagai perempuan, sebagai keturunan Afrika-Amerika, sebagai minoritas, maka Shirley akan menempuh perjuangan hingga tiga kali lebih sulit dari yang dijalaninya koleganya, para laki-laki kulit putih.
Tapi ia sudah memperhitungkan semuanya dan terus menggemakan “give politics back to the people”, kembalikan politik kepada rakyat. Sebuah pemikiran yang penuh idealisme tapi mungkin pula bisa terdengar begitu utopis.
Mungkin memang hanya sosok pendobrak seperti Shirley yang bisa mendorong pemikiran seperti itu bisa diterima oleh lebih banyak kalangan.
Dalam skenario yang ditulis John, ruang dibuka lebar bagi kita untuk melihat bagaimana Shirley masuk ke arena politik, menyesuaikan diri, memahami lawan-lawan politiknya, bahkan nyaris tewas ditikam oleh seseorang di tengah kerumunan.

Foto: Netflix
Namun sayangnya skenario tak memberi ruang cukup luas bagi kita untuk mengenali bagaimana Shirley sesungguhnya, bagaimana ia mengenal politik, memutuskan masuk ke pertarungan tak seimbang, hanya untuk pada akhirnya dikalahkan dengan tak adil.
Ini jadi sulit bagi kita untuk bersimpati pada Shirley sebagai seorang perempuan. Bahkan sebagian bisa jadi membencinya ketika diperlihatkan betapa suami yang selalu mendukungnya pun bisa disalahkannya, ditentangnya habis-habisan, dan menguras rasa cinta di antara keduanya dengan cepat.
Kita pun sulit bersimpati pada Shirley sebagai seorang keturunan Afrika-Amerika tanpa pernah diperlihatkan secara jelas apa yang pernah dilakukannya untuk kaumnya. Bahkan sebagian bisa jadi membencinya ketika melihat bahkan kakaknya sendiri, Muriel, tak mendukung pencalonannya sebagai presiden yang dianggapnya hanya menyusahkan dirinya dan ibunya semata.
Kita sulit bersimpati karena Shirley lebih banyak digambarkan oleh John sebagai ikon, bukan sebagai manusia biasa. Kita tak pernah melihatnya menangis dalam gelap dan dalam diam menyikapi pertarungan habis-habisan yang harus dijalaninya.
Kita tak pernah diberi kesempatan melihat bagaimana ia mencoba bersiasat di tengah situasi keruh rumah tangganya. Shirley Chisholm dalam Shirley hanyalah seorang politikus perempuan ambisius yang idealis, bukan manusia biasa yang melihat masalah-masalah yang ada di masyarakat yang perlu dipecahkan segera dan bisa diupayakannya ketika ia menjadi presiden kelak.

Foto: Netflix
Sebagaimana Rustin yang juga bergerak dalam skema cerita yang sama dan dengan pendekatan yang mirip, Shirley juga mudah mencuri perhatian kita karena penampilan mengagumkan dari peraih Oscar, Regina King. Susah membayangkan jika Shirley Chisholm tak diperankan olehnya.