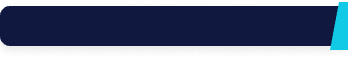Review Film Pasukan Semut: Cerita dari Tapal Batas
loading...

Film pendek Pasukan Semut menggambarkan betapa sulit dan kontrasnya kehidupan di perbatasan Indonesia-Malaysia. Foto/Gertak Film
A
A
A
JAKARTA - Tahun 2011. Saya berkesempatan menelusuri lima desa di Entikong yang menjadi perbatasan Indonesia-Malaysia dan melihat langsung kehidupan masyarakat di sana.
Penelusuran tersebut terkait dengan pembuatan film dokumenter panjang berjudul Cerita dari Tapal Batas. Saya duduk di bangku produser mengawal Wisnu Adi yang menjadi sutradara. Kami membuka masalah-masalah yang terjadi di pengujung negeri ini.
Ada tiga masalah utama yang kami identifikasi di sana, di antaranya terkait pendidikan, kesehatan, dan perdagangan manusia. Semuanya terangkum dalam Cerita dari Tapal Batas yang kelak terpilih sebagai nomine Film Dokumenter Terbaik Festival Film Indonesia(FFI) 2012.
Tepat 10 tahun kemudian, isu soal perbatasan kembali mengemuka dalam FFI. Melalui film pendek berjudul Pasukan Semut, kita melihat bahwa setelah 10 tahun belum ada perubahan signifikan yang terjadi di sana.
Kita masih melihat betapa timpangnya kehidupan masyarakat Indonesia dan Malaysia di perbatasan. Kita dipaksa melihat oleh sutradara Haris Supiandi melalui kacamata Rizal, karakter utama dalam Pasukan Semut.
![Review Film Pasukan Semut: Cerita dari Tapal Batas]()
Foto: Gertak Film
Menjadi miskin di Jakarta dan menjadi miskin di perbatasan negara sekilas tampak sama, tapi sesungguhnya sangat berbeda. Di Jakarta kita melihat komparasi pada sesama warga negara, tapi di perbatasan kita dipaksa menelan pil pahit melihat perbandingan dengan warga negara tetangga.
Saya sendiri merasakan betapa sulitnya transportasi yang selalu menjadi akar masalah di perbatasan. Karena akses yang tak memadai membuat masyarakat butuh waktu berjam-jam untuk menjual hasil bumi ke pedagang penampung. Sementara untuk ke Malaysia hanya perlu naik ojek dan langsung bertemu dengan jalan mulus bebas hambatan.
Rizal ada di tengah sengkarut masalah yang sudah berlangsung selama puluhan tahun itu. Di tengah kesulitan ekonomi ditambah dengan kondisi ibunya yang sedang sakit membuat Rizal harus mengambil keputusan: main kucing-kucingan dengan “kacang ijo”.
Istilah ini diperuntukkan bagi para tentara Indonesia yang mengawal ketat sejumlah titik di perbatasan. Oleh karena itulah Rizal menangkut gula secara ilegal demi mendapatkan penghasilan yang cukup untuk biaya pengobatan ibunya. Namun keselamatannya menjadi pertaruhan dan hidupnya pun menjadi tak tenang.
![Review Film Pasukan Semut: Cerita dari Tapal Batas]()
Foto: Gertak Film
Kita dipaksa oleh Haris masuk ke dalam hidup Rizal yang sempit di tengah negeri yang sedemikian luas hingga tak bisa terjangkau seluruhnya. Melalui storytelling yang menarik plus pengambilan gambar yang intens, kita tercebur ke dalam kubangan masalah di perbatasan bersama Rizal.
Melalui matanya, kita melihat bahwa pemerintah cenderung abai pada mereka yang hidup terlalu jauh dari pusat. Saya sendiri menyadari masalah itu ketika akhirnya tercebur ke dalam hidup masyarakat perbatasan. Bahwa negeri ini terlalu luas dan semakin diperburuk dengan kondisi wilayahnya yang terdiri dari 17 ribu pulau sehingga tak mudah dihubungkan satu sama lain.
Hidup memang sering kali hanya perlu dijalani, kadang tanpa kalkulasi berarti, sering kali juga tanpa konklusi apa pun seperti pilihan berani yang diambil oleh Haris untuk mengakhiri filmnya. Bahwa Rizal mungkin akan masih terus hidup dalam lingkaran setan kemiskinan dan terus berputar-putar di dalamnya, tanpa tahu cara untuk membebaskan diri darinya.
Bahwa banyak orang seperti Rizal yang masih mau mengambil risiko hidup merana di negeri sendiri ketimbang berpindah kewarganegaraan. Entah apa yang ada di kepala mereka yang memegang teguh ke-Indonesia-annya di tengah himpitan hidup mahasulit.
![Review Film Pasukan Semut: Cerita dari Tapal Batas]()
Foto: Gertak Film
Pada suatu hati di Entikong pada 2011 itu, kami mengambil gambar sejumlah orang tua dan anak-anaknya memanggul hasil bumi yang bisa mereka panen menyusuri desa demi desa selama berjam-jam. Kelak hasil bumi itu dijual dan sebagian ditukar dengan kebutuhan mereka mulai dari mi instan, minyak goreng, hingga roti dan kue-kue yang menjadi kemewahan mereka.
Kami mengajak mereka makan mi instan di tengah keringat yang terus mengucur dari dahi dan sekujur tubuh mereka. Tak terlihat adanya beban hidup di antara mereka. Mereka masih sempat saling bercanda dan melahap mi instan dengan nikmat.
Setiap mengingat pengalaman ini, mata saya selalu berkaca-kaca. Sering kali saya tak mensyukuri nikmat kemudahan hidup di kota besar di Jakarta. Sering kali saya hanya bisa menyumpahi sumpek dan macetnya ibu kota tanpa pernah menghargai kemudahan demi kemudahan yang diberikan olehnya.
Penelusuran tersebut terkait dengan pembuatan film dokumenter panjang berjudul Cerita dari Tapal Batas. Saya duduk di bangku produser mengawal Wisnu Adi yang menjadi sutradara. Kami membuka masalah-masalah yang terjadi di pengujung negeri ini.
Ada tiga masalah utama yang kami identifikasi di sana, di antaranya terkait pendidikan, kesehatan, dan perdagangan manusia. Semuanya terangkum dalam Cerita dari Tapal Batas yang kelak terpilih sebagai nomine Film Dokumenter Terbaik Festival Film Indonesia(FFI) 2012.
Tepat 10 tahun kemudian, isu soal perbatasan kembali mengemuka dalam FFI. Melalui film pendek berjudul Pasukan Semut, kita melihat bahwa setelah 10 tahun belum ada perubahan signifikan yang terjadi di sana.
Kita masih melihat betapa timpangnya kehidupan masyarakat Indonesia dan Malaysia di perbatasan. Kita dipaksa melihat oleh sutradara Haris Supiandi melalui kacamata Rizal, karakter utama dalam Pasukan Semut.

Foto: Gertak Film
Menjadi miskin di Jakarta dan menjadi miskin di perbatasan negara sekilas tampak sama, tapi sesungguhnya sangat berbeda. Di Jakarta kita melihat komparasi pada sesama warga negara, tapi di perbatasan kita dipaksa menelan pil pahit melihat perbandingan dengan warga negara tetangga.
Saya sendiri merasakan betapa sulitnya transportasi yang selalu menjadi akar masalah di perbatasan. Karena akses yang tak memadai membuat masyarakat butuh waktu berjam-jam untuk menjual hasil bumi ke pedagang penampung. Sementara untuk ke Malaysia hanya perlu naik ojek dan langsung bertemu dengan jalan mulus bebas hambatan.
Rizal ada di tengah sengkarut masalah yang sudah berlangsung selama puluhan tahun itu. Di tengah kesulitan ekonomi ditambah dengan kondisi ibunya yang sedang sakit membuat Rizal harus mengambil keputusan: main kucing-kucingan dengan “kacang ijo”.
Istilah ini diperuntukkan bagi para tentara Indonesia yang mengawal ketat sejumlah titik di perbatasan. Oleh karena itulah Rizal menangkut gula secara ilegal demi mendapatkan penghasilan yang cukup untuk biaya pengobatan ibunya. Namun keselamatannya menjadi pertaruhan dan hidupnya pun menjadi tak tenang.

Foto: Gertak Film
Kita dipaksa oleh Haris masuk ke dalam hidup Rizal yang sempit di tengah negeri yang sedemikian luas hingga tak bisa terjangkau seluruhnya. Melalui storytelling yang menarik plus pengambilan gambar yang intens, kita tercebur ke dalam kubangan masalah di perbatasan bersama Rizal.
Melalui matanya, kita melihat bahwa pemerintah cenderung abai pada mereka yang hidup terlalu jauh dari pusat. Saya sendiri menyadari masalah itu ketika akhirnya tercebur ke dalam hidup masyarakat perbatasan. Bahwa negeri ini terlalu luas dan semakin diperburuk dengan kondisi wilayahnya yang terdiri dari 17 ribu pulau sehingga tak mudah dihubungkan satu sama lain.
Hidup memang sering kali hanya perlu dijalani, kadang tanpa kalkulasi berarti, sering kali juga tanpa konklusi apa pun seperti pilihan berani yang diambil oleh Haris untuk mengakhiri filmnya. Bahwa Rizal mungkin akan masih terus hidup dalam lingkaran setan kemiskinan dan terus berputar-putar di dalamnya, tanpa tahu cara untuk membebaskan diri darinya.
Bahwa banyak orang seperti Rizal yang masih mau mengambil risiko hidup merana di negeri sendiri ketimbang berpindah kewarganegaraan. Entah apa yang ada di kepala mereka yang memegang teguh ke-Indonesia-annya di tengah himpitan hidup mahasulit.

Foto: Gertak Film
Pada suatu hati di Entikong pada 2011 itu, kami mengambil gambar sejumlah orang tua dan anak-anaknya memanggul hasil bumi yang bisa mereka panen menyusuri desa demi desa selama berjam-jam. Kelak hasil bumi itu dijual dan sebagian ditukar dengan kebutuhan mereka mulai dari mi instan, minyak goreng, hingga roti dan kue-kue yang menjadi kemewahan mereka.
Kami mengajak mereka makan mi instan di tengah keringat yang terus mengucur dari dahi dan sekujur tubuh mereka. Tak terlihat adanya beban hidup di antara mereka. Mereka masih sempat saling bercanda dan melahap mi instan dengan nikmat.
Setiap mengingat pengalaman ini, mata saya selalu berkaca-kaca. Sering kali saya tak mensyukuri nikmat kemudahan hidup di kota besar di Jakarta. Sering kali saya hanya bisa menyumpahi sumpek dan macetnya ibu kota tanpa pernah menghargai kemudahan demi kemudahan yang diberikan olehnya.