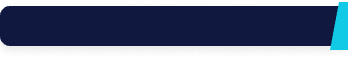CERMIN: Lagi-Lagi Kejutan dari Malaysia
loading...

Film Malaysia La Luna menyajikan premis menggelitik tentang toko pakaian dalam perempuan yang ada di desa konservatif. Foto/Golden Village
A
A
A
JAKARTA - Tahun 2023. Tiga judul film Malaysia hadir di tengah kebosanan penonton film Indonesia dengan semakin tak menariknya materi cerita sebagian film dari negerinya sendiri.
Pendatang menjadi sebuah anomali dari Malaysia dengan genre thriller distopia yang memperlihatkan bagaimana Malaysia terpecah belah setelah Undang-Undang Segregasi diberlakukan. Sebagaimana yang kita tahu, di Malaysia bermukim sejumlah etnis mulai dari Melayu, Tionghoa, hingga India.
Dalam imajinasi penulis skenarionya, Boon Siang Lim, suatu saat isu etnis akan meledak dan memecah belah negeri itu. Dan selama 98 menit kita diperlihatkan betapa mengerikannya ketika segregasi terjadi, sebagaimana yang sering kita lihat terjadi dalam film-film Hollywood berlatar tahun 1950-1960-an.
Sebelumnya ada Tiger Stripes dari sutradara Amanda Nell Eu yang beroleh penghargaan prestisius Grand Jury Prize dari Cannes International Critics Week pada Mei lalu. Tiger Stripes juga sebuah anomali ketika Amanda menceritakan secara eksperimental bagaimana pengalaman seorang remaja perempuan mengalami menstruasi pertamanya dan berujung pada metamorfosa si remaja menjadi makhluk jadi-jadian.
Tiger Stripes hadir dalam rangkaian Jakarta Film Week yang digelar di CGV Grand Indonesia pada Oktober 2023 lalu, sementara Pendatang diputar secara daring di KlikFilm dalam rangkaian Jogja-Netpac Asian Film Festival (JAFF) 2023 yang baru saja berlangsung. Kini La Luna hadir secara reguler di bioskop dan menjadi kesempatan langka menyaksikan film dari Negeri Jiran tersebut di layar besar.
![CERMIN: Lagi-Lagi Kejutan dari Malaysia]()
Foto: Golden Village
Tapi La Luna memang pantas disaksikan di layar besar. Siapa yang tak tergelitik dengan premisnya tentang kehadiran toko pakaian dalam perempuan yang hadir di sebuah desa yang sangat Islami dan kelak mengguncang sendi-sendi kehidupan di dalamnya.
Di tangan sutradara Raihan Halim, kritik soal susahnya kita menerima perubahan bisa tersampaikan dengan begitu jenaka tapi pada saat bersamaan juga bisa begitu jernih dan telak. Tak tercium pretensi untuk menceramahi penonton akan terjadinya pergeseran nilai karena kita melihat Raihan sekadar menghidangkan apa yang sebenarnya sudah kita ketahui, mungkin juga kita alami, dengan lebih jelas di depan mata kita.
Desa Bras Basah adalah sebuah desa yang mencoba menjalankan syariat Islam secara ketat, bisa juga secara keterlaluan. Tuhan dipersonifikasi sebagai sosok yang menakutkan sebagai jalan bagi penguasa untuk mendikte pemikiran warganya. Penguasa bahkan merasa perlu memberlakukan sensor demi menjaga kesucian desa yang jika perlu ditundukkan dengan tangan besi.
Masjid pun sering kali digunakan sebagai tempat untuk mendikte pemikiran yang jelas sekali bertentangan dengan ajaran Islam yang justru menyuruh kita "membaca”. Tapi pada hari-hari-hari ini, ketika era keterbukaan informasi menggema di seluruh dunia, masih relevankah sensor dan dikte? Apa urgensi menyeragamkan isi kepala masyarakat dan mengatur tata perilaku mereka secara keseluruhan?
Datuk Hassan menjadi sosok penguasa bengis itu. Ia hanya mempercayai nilai-nilai yang diyakininya. Sebagai penguasa desa, ia memaksakan nilai-nilai itu kepada warganya dan membuat mereka tunduk selama bertahun-tahun tanpa berani melakukan protes secara terbuka.
![CERMIN: Lagi-Lagi Kejutan dari Malaysia]()
Foto: Golden Village
Hingga suatu hari seorang perempuan tak berhijab, namanya Hanie Abdullah, datang ke desa itu dan membuka toko pakaian dalam perempuan di sana. Hanie datang ke desa itu karena punya keterikatan kekeluargaan. Ia adalah cucu dari tokoh masyarakat di sana dan bangunan yang digunakannya membuka toko adalah warisan dari kakeknya.
Tak ada yang salah dengan itu, tak ada yang aneh dengan itu. Buat kita yang hidup di masyarakat modern, justru aneh melihat Datuk Hassan seperti kebakaran jenggot ketika melihat toko tersebut dianggapnya akan mencoreng kesucian desa yang sudah dijaganya selama bertahun-tahun.
Pelan-pelan kita tahu warga sesungguhnya sudah lama ingin berontak dengan kekangan dari aturan-aturan yang dibuat Datuk Hassan untuk desa itu. Maka kehadiran toko yang kemudian diberi nama La Luna itu menjadi katalis.
Bibit-bibit pemberontakan yang sesungguhnya sudah ada itu pelan-pelan mencari sumbunya. Tapi perubahan memang tak bisa datang dalam semalam. Dan warga pun masih menghormati Datuk Hassan.
![CERMIN: Lagi-Lagi Kejutan dari Malaysia]()
Foto: Golden Village
Pelan-pelan pula kita melihat Raihan menggeser La Luna dari komedi pengocok tawa menjadi sebuah kritik sosial yang sesungguhnya pedas. Skenario yang dirakit Raihan secara brilian menangkap bagaimana La Luna menjadi semacam pelampiasan keterkungkungan selama bertahun-tahun itu.
Kita juga melihat La Luna berubah menjadi tempat aman bagi perempuan yang mengalami KDRT dari suaminya. Sebagaimana yang diucapkan Hanie ketika ditanya kenapa lampu penanda La Luna yang terang benderang perlu menyala sepanjang malam, ia menjawab bahwa pada suatu masa lampu penanda itu diartikan sebagian perempuan pelanggannya sebagai beacon of hope (suar harapan). Selama lampu itu menyala, selama itu pula ada ruang aman bagi perempuan untuk menyelamatkan diri dari kemalangan yang hendak menimpanya.
Pendatang menjadi sebuah anomali dari Malaysia dengan genre thriller distopia yang memperlihatkan bagaimana Malaysia terpecah belah setelah Undang-Undang Segregasi diberlakukan. Sebagaimana yang kita tahu, di Malaysia bermukim sejumlah etnis mulai dari Melayu, Tionghoa, hingga India.
Dalam imajinasi penulis skenarionya, Boon Siang Lim, suatu saat isu etnis akan meledak dan memecah belah negeri itu. Dan selama 98 menit kita diperlihatkan betapa mengerikannya ketika segregasi terjadi, sebagaimana yang sering kita lihat terjadi dalam film-film Hollywood berlatar tahun 1950-1960-an.
Sebelumnya ada Tiger Stripes dari sutradara Amanda Nell Eu yang beroleh penghargaan prestisius Grand Jury Prize dari Cannes International Critics Week pada Mei lalu. Tiger Stripes juga sebuah anomali ketika Amanda menceritakan secara eksperimental bagaimana pengalaman seorang remaja perempuan mengalami menstruasi pertamanya dan berujung pada metamorfosa si remaja menjadi makhluk jadi-jadian.
Tiger Stripes hadir dalam rangkaian Jakarta Film Week yang digelar di CGV Grand Indonesia pada Oktober 2023 lalu, sementara Pendatang diputar secara daring di KlikFilm dalam rangkaian Jogja-Netpac Asian Film Festival (JAFF) 2023 yang baru saja berlangsung. Kini La Luna hadir secara reguler di bioskop dan menjadi kesempatan langka menyaksikan film dari Negeri Jiran tersebut di layar besar.

Foto: Golden Village
Tapi La Luna memang pantas disaksikan di layar besar. Siapa yang tak tergelitik dengan premisnya tentang kehadiran toko pakaian dalam perempuan yang hadir di sebuah desa yang sangat Islami dan kelak mengguncang sendi-sendi kehidupan di dalamnya.
Di tangan sutradara Raihan Halim, kritik soal susahnya kita menerima perubahan bisa tersampaikan dengan begitu jenaka tapi pada saat bersamaan juga bisa begitu jernih dan telak. Tak tercium pretensi untuk menceramahi penonton akan terjadinya pergeseran nilai karena kita melihat Raihan sekadar menghidangkan apa yang sebenarnya sudah kita ketahui, mungkin juga kita alami, dengan lebih jelas di depan mata kita.
Desa Bras Basah adalah sebuah desa yang mencoba menjalankan syariat Islam secara ketat, bisa juga secara keterlaluan. Tuhan dipersonifikasi sebagai sosok yang menakutkan sebagai jalan bagi penguasa untuk mendikte pemikiran warganya. Penguasa bahkan merasa perlu memberlakukan sensor demi menjaga kesucian desa yang jika perlu ditundukkan dengan tangan besi.
Masjid pun sering kali digunakan sebagai tempat untuk mendikte pemikiran yang jelas sekali bertentangan dengan ajaran Islam yang justru menyuruh kita "membaca”. Tapi pada hari-hari-hari ini, ketika era keterbukaan informasi menggema di seluruh dunia, masih relevankah sensor dan dikte? Apa urgensi menyeragamkan isi kepala masyarakat dan mengatur tata perilaku mereka secara keseluruhan?
Datuk Hassan menjadi sosok penguasa bengis itu. Ia hanya mempercayai nilai-nilai yang diyakininya. Sebagai penguasa desa, ia memaksakan nilai-nilai itu kepada warganya dan membuat mereka tunduk selama bertahun-tahun tanpa berani melakukan protes secara terbuka.

Foto: Golden Village
Hingga suatu hari seorang perempuan tak berhijab, namanya Hanie Abdullah, datang ke desa itu dan membuka toko pakaian dalam perempuan di sana. Hanie datang ke desa itu karena punya keterikatan kekeluargaan. Ia adalah cucu dari tokoh masyarakat di sana dan bangunan yang digunakannya membuka toko adalah warisan dari kakeknya.
Tak ada yang salah dengan itu, tak ada yang aneh dengan itu. Buat kita yang hidup di masyarakat modern, justru aneh melihat Datuk Hassan seperti kebakaran jenggot ketika melihat toko tersebut dianggapnya akan mencoreng kesucian desa yang sudah dijaganya selama bertahun-tahun.
Pelan-pelan kita tahu warga sesungguhnya sudah lama ingin berontak dengan kekangan dari aturan-aturan yang dibuat Datuk Hassan untuk desa itu. Maka kehadiran toko yang kemudian diberi nama La Luna itu menjadi katalis.
Bibit-bibit pemberontakan yang sesungguhnya sudah ada itu pelan-pelan mencari sumbunya. Tapi perubahan memang tak bisa datang dalam semalam. Dan warga pun masih menghormati Datuk Hassan.

Foto: Golden Village
Pelan-pelan pula kita melihat Raihan menggeser La Luna dari komedi pengocok tawa menjadi sebuah kritik sosial yang sesungguhnya pedas. Skenario yang dirakit Raihan secara brilian menangkap bagaimana La Luna menjadi semacam pelampiasan keterkungkungan selama bertahun-tahun itu.
Kita juga melihat La Luna berubah menjadi tempat aman bagi perempuan yang mengalami KDRT dari suaminya. Sebagaimana yang diucapkan Hanie ketika ditanya kenapa lampu penanda La Luna yang terang benderang perlu menyala sepanjang malam, ia menjawab bahwa pada suatu masa lampu penanda itu diartikan sebagian perempuan pelanggannya sebagai beacon of hope (suar harapan). Selama lampu itu menyala, selama itu pula ada ruang aman bagi perempuan untuk menyelamatkan diri dari kemalangan yang hendak menimpanya.