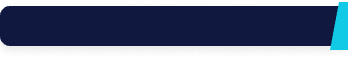CERMIN: Hidup yang Kita Alami Memang Tak Seperti dalam Film-Film
loading...

Film Jatuh Cinta Seperti di Film-Film menjadi angin segar bagi perfilman Indonesia yang temanya mulai monoton. Foto/Imajinari
A
A
A
JAKARTA - Tahun 2045. Saat Indonesia berhasil menggapai Indonesia Emas yang sudah diimpikan puluhan tahun sebelumnya, saya malah tak bisa memisahkan antara hidup yang saya tulis dan sutradarai dalam film dan hidup yang saya jalani keseharian.
Dalam usia 60-an tahun, saya masih berkarya dengan menjadi sutradara, sesekali memproduseri sutradara-sutradara muda cemerlang, sesekali pula menulis sendiri skenario yang entah kelak saya sutradarai sendiri atau malah diminati sutradara-sutradara muda lainnya.
Tapi yang menjadi masalah besar bagi saya, mungkin juga semacam kutukan bagi saya, ketika mencoba-coba menulis skenario adalah saya semakin tak bisa memisahkan antara hidup dalam film dan hidup yang saya jalani sehari-hari. Batasnya semakin kabur dan saya terjebak dalam dunia meta-realitas.
Pada 2023, saya sempat menyaksikan film garapan sutradara muda yang sama-sama berasal dari Makassar seperti saya, Yandy Laurens. Filmnya berjudul unik, Jatuh Cinta Seperti di Film-Film dan tiba-tiba saya dibawa Yandy memasuki sebuah dunia meta-realitas yang meyakinkan saya kelak, mungkin saya bisa bernasib seperti ketakutan saya di atas. Tapi Yandy meyakinkan saya bahwa sering kali hidup memang tak semudah (juga mungkin tak sesulit?) seperti dalam film-film.
Jatuh Cinta Seperti di Film-Film hadir bak oase di tengah gurun tandus perfilman nasional. Ketika semakin banyak dari kami, para sineas, yang terpaksa mengerjakan cerita yang begitu-begitu saja, berkutat pada genre yang itu-itu saja karena dianggap selalu laku dan akhirnya terkurung dalam lingkaran setan kehidupan yang begitu-begitu saja.
![CERMIN: Hidup yang Kita Alami Memang Tak Seperti dalam Film-Film]()
Foto: Imajinari
Tapi Yandy datang dengan sebuah cerita yang meyakinkan saya, juga saya yakin banyak orang, bahwa film Indonesia tak seragam, film Indonesia tak harus diproduksi satu warna. Karena itulah Jatuh Cinta Seperti di Film-Film tak sekadar berani menyodorkan cerita yang belum pernah dibuat di negeri ini, tapi juga pendekatan sinematik berupa pewarnaan hitam putih hampir sepanjang durasi film.
Yandy membawa kita memasuki semesta berpikir cerita yang ada dalam film-film. Kita diajak berkenalan dengan Bagus (Ringgo Agus Rahman, yang semakin matang berakting), seorang penulis skenario. Sepanjang kariernya, Bagus menulis skenario adaptasi, entah dari sinetron sukses atau materi-materi lainnya.
Pada satu titik dalam hidupnya, Bagus ingin bercerita. Sebuah kisah yang datang dari dirinya. Sebuah kisah romansa. Juga sebuah rencana baginya untuk menjadikannya kado bagi pujaan hatinya.
Dalam kisah yang ditulisnya, Bagus bertemu pujaan hatinya pada sebuah hari biasa di salah satu supermarket. Namanya Hana (dimainkan Nirina Zubir, yang berpeluang besar membawa pulang Piala Citra yang kedua tahun depan). Sebagai penonton laki-laki, sejak pertama kali kita bertemu Hana, saya paham mengapa Bagus menyukainya.
Saya tak bisa menjelaskannya dengan gamblang dan skenario yang ditulis Yandy pun rasanya memang tak perlu menjelaskannya. Bagus tak berbinar-binar menatap Hana, Hana pun bersikap biasa saja terhadap Bagus. Tapi daya magis film bekerja dalam film ini yang membuat kita tahu ada api yang masih menyala dalam dada Bagus.
![CERMIN: Hidup yang Kita Alami Memang Tak Seperti dalam Film-Film]()
Foto: Imajinari
Karena itulah, sejak saat itu Bagus dan Hana semakin sering bertemu, Hana pun membiarkan dirinya yang baru saja menjanda membuka dirinya perlahan. Yang Hana tak pernah tahu sejak awal bahwa Bagus akan menuliskan semua yang mereka jalani ke dalam skenario film yang kelak akan disutradarainya sendiri.
Saya pun kelak membiarkan diri saya membayangkan menjadi Bagus. Bagaimana rasanya menjadi seseorang yang dengan alasan yang salah mencoba menuliskan kisah hidup seseorang tanpa seizinnya.
Saya masuk ke dalam dunia Bagus yang merasakan frustrasi (yang memang pernah saya alami sendiri) tatkala merasa skenario yang ditulis tak sebagus yang dibayangkan. Saya mencoba berpikir seperti Bagus yang menganggap film yang dibuatnya kali ini sebagai kado terindah untuk Hana sekaligus menjadi kejutan manis buatnya.
Sayangnya saya tak mencoba membayangkan diri saya menjadi Hana. Dengan segala luka yang belum pulih ditinggal suami. Dengan keinginan untuk tak ingin beranjak dari hidup yang tetap mengajaknya kembali berjalan. Dan meyakini bahwa karena kepahitan sudah terasakan dalam hidup, bolehkah kita mencicipi manisnya cinta di akhir kisah romansa?
![CERMIN: Hidup yang Kita Alami Memang Tak Seperti dalam Film-Film]()
Foto: Imajinari
Rekandi rumah produksi saya, Irfan Syam, pernah iseng menghitung berapa banyak saya memasukkan soal kematian dalam film/serial/miniseri yang pernah saya produseri dan sutradarai. Ternyata cukup banyak. Mungkin memang karena sejak usia remaja, saya sudah merasakannya dan melihatnya sebagai bagian alamiah dari hidup.
Jatuh Cinta Seperti di Film-Film membuat saya kembali membayangkan rasanya jatuh cinta untuk kesekian kalinya dengan sinema. Menjadikannya sebagai bagian dari aliran darah yang mengairi hidup saya, meski dengan konsekuensi bahwa dalam usia 60-an kelak, mungkin saya akan punya kesulitan memisahkan antara hidup dalam film dengan hidup yang saya jalani.
Dalam usia 60-an tahun, saya masih berkarya dengan menjadi sutradara, sesekali memproduseri sutradara-sutradara muda cemerlang, sesekali pula menulis sendiri skenario yang entah kelak saya sutradarai sendiri atau malah diminati sutradara-sutradara muda lainnya.
Tapi yang menjadi masalah besar bagi saya, mungkin juga semacam kutukan bagi saya, ketika mencoba-coba menulis skenario adalah saya semakin tak bisa memisahkan antara hidup dalam film dan hidup yang saya jalani sehari-hari. Batasnya semakin kabur dan saya terjebak dalam dunia meta-realitas.
Pada 2023, saya sempat menyaksikan film garapan sutradara muda yang sama-sama berasal dari Makassar seperti saya, Yandy Laurens. Filmnya berjudul unik, Jatuh Cinta Seperti di Film-Film dan tiba-tiba saya dibawa Yandy memasuki sebuah dunia meta-realitas yang meyakinkan saya kelak, mungkin saya bisa bernasib seperti ketakutan saya di atas. Tapi Yandy meyakinkan saya bahwa sering kali hidup memang tak semudah (juga mungkin tak sesulit?) seperti dalam film-film.
Jatuh Cinta Seperti di Film-Film hadir bak oase di tengah gurun tandus perfilman nasional. Ketika semakin banyak dari kami, para sineas, yang terpaksa mengerjakan cerita yang begitu-begitu saja, berkutat pada genre yang itu-itu saja karena dianggap selalu laku dan akhirnya terkurung dalam lingkaran setan kehidupan yang begitu-begitu saja.

Foto: Imajinari
Tapi Yandy datang dengan sebuah cerita yang meyakinkan saya, juga saya yakin banyak orang, bahwa film Indonesia tak seragam, film Indonesia tak harus diproduksi satu warna. Karena itulah Jatuh Cinta Seperti di Film-Film tak sekadar berani menyodorkan cerita yang belum pernah dibuat di negeri ini, tapi juga pendekatan sinematik berupa pewarnaan hitam putih hampir sepanjang durasi film.
Yandy membawa kita memasuki semesta berpikir cerita yang ada dalam film-film. Kita diajak berkenalan dengan Bagus (Ringgo Agus Rahman, yang semakin matang berakting), seorang penulis skenario. Sepanjang kariernya, Bagus menulis skenario adaptasi, entah dari sinetron sukses atau materi-materi lainnya.
Pada satu titik dalam hidupnya, Bagus ingin bercerita. Sebuah kisah yang datang dari dirinya. Sebuah kisah romansa. Juga sebuah rencana baginya untuk menjadikannya kado bagi pujaan hatinya.
Dalam kisah yang ditulisnya, Bagus bertemu pujaan hatinya pada sebuah hari biasa di salah satu supermarket. Namanya Hana (dimainkan Nirina Zubir, yang berpeluang besar membawa pulang Piala Citra yang kedua tahun depan). Sebagai penonton laki-laki, sejak pertama kali kita bertemu Hana, saya paham mengapa Bagus menyukainya.
Saya tak bisa menjelaskannya dengan gamblang dan skenario yang ditulis Yandy pun rasanya memang tak perlu menjelaskannya. Bagus tak berbinar-binar menatap Hana, Hana pun bersikap biasa saja terhadap Bagus. Tapi daya magis film bekerja dalam film ini yang membuat kita tahu ada api yang masih menyala dalam dada Bagus.

Foto: Imajinari
Karena itulah, sejak saat itu Bagus dan Hana semakin sering bertemu, Hana pun membiarkan dirinya yang baru saja menjanda membuka dirinya perlahan. Yang Hana tak pernah tahu sejak awal bahwa Bagus akan menuliskan semua yang mereka jalani ke dalam skenario film yang kelak akan disutradarainya sendiri.
Saya pun kelak membiarkan diri saya membayangkan menjadi Bagus. Bagaimana rasanya menjadi seseorang yang dengan alasan yang salah mencoba menuliskan kisah hidup seseorang tanpa seizinnya.
Saya masuk ke dalam dunia Bagus yang merasakan frustrasi (yang memang pernah saya alami sendiri) tatkala merasa skenario yang ditulis tak sebagus yang dibayangkan. Saya mencoba berpikir seperti Bagus yang menganggap film yang dibuatnya kali ini sebagai kado terindah untuk Hana sekaligus menjadi kejutan manis buatnya.
Sayangnya saya tak mencoba membayangkan diri saya menjadi Hana. Dengan segala luka yang belum pulih ditinggal suami. Dengan keinginan untuk tak ingin beranjak dari hidup yang tetap mengajaknya kembali berjalan. Dan meyakini bahwa karena kepahitan sudah terasakan dalam hidup, bolehkah kita mencicipi manisnya cinta di akhir kisah romansa?

Foto: Imajinari
Rekandi rumah produksi saya, Irfan Syam, pernah iseng menghitung berapa banyak saya memasukkan soal kematian dalam film/serial/miniseri yang pernah saya produseri dan sutradarai. Ternyata cukup banyak. Mungkin memang karena sejak usia remaja, saya sudah merasakannya dan melihatnya sebagai bagian alamiah dari hidup.
Jatuh Cinta Seperti di Film-Film membuat saya kembali membayangkan rasanya jatuh cinta untuk kesekian kalinya dengan sinema. Menjadikannya sebagai bagian dari aliran darah yang mengairi hidup saya, meski dengan konsekuensi bahwa dalam usia 60-an kelak, mungkin saya akan punya kesulitan memisahkan antara hidup dalam film dengan hidup yang saya jalani.