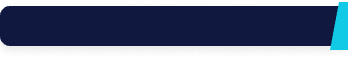CERMIN: Kisah Romeo dan Juliet Versi PKI
loading...

Film Kupu-Kupu Kertas ibarat kisah Romeo dan Juliet dengan karakter terkait PKI dan GP Ansor. Foto/Maxima Pictures
A
A
A
JAKARTA - Tahun 1597. William Shakespeare mempublikasikan drama Romeo and Juliet yang sesungguhnya bukan murni hasil karyanya.
Kisah tentang dua anak muda yang saling mencintai di tengah dua keluarganya yang saling bermusuhan itu meminjam plot dari kisah Italia yang ditulis Matteo Bandello, dan diterjemahkan ke dalam syair berjudul The Tragical History of Romeus and Juliet oleh Arthur Brooke pada 1562. Kisah ini lantas diceritakan kembali dalam bentuk prosa berjudul Palace of Pleasure oleh William Painter pada 1567.
William banyak meminjam inspirasi dari kedua tulisan di atas, tapi memperluas plot dengan mengembangkan sejumlah karakter pendukung, khususnya Mercutio dan Paris. Kisah Romeo dan Juliet lantas menjadi klasik dan diadaptasi menjadi film dalam berbagai periode dari tahun 1936 oleh George Cukor, tahun 1968 oleh Franco Zeffirelli, dan bisa jadi yang paling terkenal pada tahun 1996 oleh Baz Luhrmann.
Produser Denny Siregar yang mencuri perhatian dengan debutnya dalam film Sayap-Sayap Patah(2022) meminjam plot dari Romeo dan Juliet dan menginjeksikannya ke dalam cerita berlatar tahun 1965 di Banyuwangi berjudul puitis, Kupu-Kupu Kertas. Kisahnya diolah oleh duet penulis skenario Rahabi Mandra dan Jocelyn Coroelia.
Sutradara Emil Heradi tak membuang waktu, langsung mempertemukan kita dengan dua karakter utama sejak menit awal film dibuka. Ada Ning, seorang perawat yang anak seorang simpatisan PKI dan Ikhsan, adik dari aktivis GP Ansor.
![CERMIN: Kisah Romeo dan Juliet Versi PKI]()
Foto: Maxima Pictures
Kita melihat pertemuan keduanya, melihat bagaimana mereka membuka hati satu sama lain di tengah kekacauan yang tengah terjadi. Mereka mengambil risiko untuk menjaga kesucian cinta mereka dan kelak memperjuangkannya hingga mati.
Tapi ketika kita sebagai penonton merasa kurang bersimpati pada perjalanan cinta mereka, maka terasa ada sesuatu yang salah. Bisa jadi karena beberapa alasan yang logis. Pertama, kita melihat Ning dan Ikhsan pertama kali menjalin hubungan di tengah kekacauan dan sesungguhnya sedari awal mereka sudah tahu risikonya.
Dalam durasinya yang 113 menit, skenario tak pernah memperlihatkan kepada penonton mengapa hubungan mereka layak dipertahankan mati-matian. Akhirnya memang kita melihat Amanda Manopo dan Chicco Kurniawan yang meski berusaha mati-matian memainkan karakternya sepenuh hati, tetap saja kurang terasa jalinan kimiawi di antara mereka berdua yang sampai ke hati penonton.
Kedua, sangat disayangkan cerita yang meminjam latar kekacauan yang terjadi antara GP Ansor dan PKI di Banyuwangi pada 1965, tapi abai menginjeksi detail-detail menarik yang bisa membuat filmnya menjadi lebih dramatik dan terasa lebih bernyawa. Padahal ada banyak hal yang bisa digali dan menjadi informasi baru bagi penonton.
![CERMIN: Kisah Romeo dan Juliet Versi PKI]()
Foto: Maxima Pictures
Sayangnya, hingga film berakhir hal tersebut tak tersajikan. Sekali lagi kita hanya melihat kisah cinta Ning dan Ikhsan yang terasa kosong dan over-melodramatic di tengah kekacauan.
Ketiga, dan mungkin yang paling fatal, adalah keputusan untuk membuat karakter Ikhsan sebagai tokoh yang sesungguhnya sangat lemah dalam bingkai cerita. Ia hanya punya relasi sebagai adik dari Rasyid, tokoh GP Ansor dan memilih tak terlibat dalam kekacauan yang terjadi di sekelilingnya.
Dengan pilihan senekat ini, apa pun yang terjadi pada Ikhsan, bisa jadi kita tak mempedulikannya. Karena Ikhsan pun memilih tak peduli pada apa pun yang terjadi di sekitarnya, ia hanya terlihat sebagai cowok bucin yang egois.
Namunyang selalu menarik dalam sejumlah film Indonesia yang lemah dalam skenario adalah bahwa sinematografi justru terasa menonjol. Di tangan Padri Nadeak yang sudah beroleh dua nomine Piala Citra untuk film Rumah di Seribu Ombak dan Dua Garis Biru, gambar-gambar yang dirakitnya dalam Kupu-Kupu Kertas menjelma bak lukisan nan magis.
![CERMIN: Kisah Romeo dan Juliet Versi PKI]()
Foto: Maxima Pictures
Nyaris tak ada gambar yang tak diorkestrasi untuk hadir dengan komposisi yang enak dipandang. Tentu saja kerja keras dari Padri menutupi lemahnya film ini dari sisi penceritaan.
Padahal dengan nama Denny Siregar sebagai produser, saya berharap Kupu-Kupu Kertas memberikan lebih banyak perspektif menarik seputar bentrokan antara GP Ansor dan PKI yang konon menelan korban ribuan manusia.
Andang Chatif Yusuf yang merupakan Sekretaris Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) Banyuwangi pernah menuturkan kepada Tempo bahwa jumlah korban dari pihak PKI diperkirakan mencapai ribuan nyawa. Padahal dengan nama Denny Siregar sebagai produser, saya juga berharap Kupu-Kupu Kertas memberi gambaran lebih berani seputar Operasi Gagak Hitam yang sempat menghebohkan kala itu.
Kisah tentang dua anak muda yang saling mencintai di tengah dua keluarganya yang saling bermusuhan itu meminjam plot dari kisah Italia yang ditulis Matteo Bandello, dan diterjemahkan ke dalam syair berjudul The Tragical History of Romeus and Juliet oleh Arthur Brooke pada 1562. Kisah ini lantas diceritakan kembali dalam bentuk prosa berjudul Palace of Pleasure oleh William Painter pada 1567.
William banyak meminjam inspirasi dari kedua tulisan di atas, tapi memperluas plot dengan mengembangkan sejumlah karakter pendukung, khususnya Mercutio dan Paris. Kisah Romeo dan Juliet lantas menjadi klasik dan diadaptasi menjadi film dalam berbagai periode dari tahun 1936 oleh George Cukor, tahun 1968 oleh Franco Zeffirelli, dan bisa jadi yang paling terkenal pada tahun 1996 oleh Baz Luhrmann.
Produser Denny Siregar yang mencuri perhatian dengan debutnya dalam film Sayap-Sayap Patah(2022) meminjam plot dari Romeo dan Juliet dan menginjeksikannya ke dalam cerita berlatar tahun 1965 di Banyuwangi berjudul puitis, Kupu-Kupu Kertas. Kisahnya diolah oleh duet penulis skenario Rahabi Mandra dan Jocelyn Coroelia.
Sutradara Emil Heradi tak membuang waktu, langsung mempertemukan kita dengan dua karakter utama sejak menit awal film dibuka. Ada Ning, seorang perawat yang anak seorang simpatisan PKI dan Ikhsan, adik dari aktivis GP Ansor.

Foto: Maxima Pictures
Kita melihat pertemuan keduanya, melihat bagaimana mereka membuka hati satu sama lain di tengah kekacauan yang tengah terjadi. Mereka mengambil risiko untuk menjaga kesucian cinta mereka dan kelak memperjuangkannya hingga mati.
Tapi ketika kita sebagai penonton merasa kurang bersimpati pada perjalanan cinta mereka, maka terasa ada sesuatu yang salah. Bisa jadi karena beberapa alasan yang logis. Pertama, kita melihat Ning dan Ikhsan pertama kali menjalin hubungan di tengah kekacauan dan sesungguhnya sedari awal mereka sudah tahu risikonya.
Dalam durasinya yang 113 menit, skenario tak pernah memperlihatkan kepada penonton mengapa hubungan mereka layak dipertahankan mati-matian. Akhirnya memang kita melihat Amanda Manopo dan Chicco Kurniawan yang meski berusaha mati-matian memainkan karakternya sepenuh hati, tetap saja kurang terasa jalinan kimiawi di antara mereka berdua yang sampai ke hati penonton.
Kedua, sangat disayangkan cerita yang meminjam latar kekacauan yang terjadi antara GP Ansor dan PKI di Banyuwangi pada 1965, tapi abai menginjeksi detail-detail menarik yang bisa membuat filmnya menjadi lebih dramatik dan terasa lebih bernyawa. Padahal ada banyak hal yang bisa digali dan menjadi informasi baru bagi penonton.

Foto: Maxima Pictures
Sayangnya, hingga film berakhir hal tersebut tak tersajikan. Sekali lagi kita hanya melihat kisah cinta Ning dan Ikhsan yang terasa kosong dan over-melodramatic di tengah kekacauan.
Ketiga, dan mungkin yang paling fatal, adalah keputusan untuk membuat karakter Ikhsan sebagai tokoh yang sesungguhnya sangat lemah dalam bingkai cerita. Ia hanya punya relasi sebagai adik dari Rasyid, tokoh GP Ansor dan memilih tak terlibat dalam kekacauan yang terjadi di sekelilingnya.
Dengan pilihan senekat ini, apa pun yang terjadi pada Ikhsan, bisa jadi kita tak mempedulikannya. Karena Ikhsan pun memilih tak peduli pada apa pun yang terjadi di sekitarnya, ia hanya terlihat sebagai cowok bucin yang egois.
Namunyang selalu menarik dalam sejumlah film Indonesia yang lemah dalam skenario adalah bahwa sinematografi justru terasa menonjol. Di tangan Padri Nadeak yang sudah beroleh dua nomine Piala Citra untuk film Rumah di Seribu Ombak dan Dua Garis Biru, gambar-gambar yang dirakitnya dalam Kupu-Kupu Kertas menjelma bak lukisan nan magis.

Foto: Maxima Pictures
Nyaris tak ada gambar yang tak diorkestrasi untuk hadir dengan komposisi yang enak dipandang. Tentu saja kerja keras dari Padri menutupi lemahnya film ini dari sisi penceritaan.
Padahal dengan nama Denny Siregar sebagai produser, saya berharap Kupu-Kupu Kertas memberikan lebih banyak perspektif menarik seputar bentrokan antara GP Ansor dan PKI yang konon menelan korban ribuan manusia.
Andang Chatif Yusuf yang merupakan Sekretaris Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) Banyuwangi pernah menuturkan kepada Tempo bahwa jumlah korban dari pihak PKI diperkirakan mencapai ribuan nyawa. Padahal dengan nama Denny Siregar sebagai produser, saya juga berharap Kupu-Kupu Kertas memberi gambaran lebih berani seputar Operasi Gagak Hitam yang sempat menghebohkan kala itu.