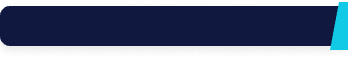CERMIN: Monster Itu Bernama Prasangka
loading...

Film Jepang Monster menampilkan kisah dari sudut pandang berbeda dengan benang merah tentang prasangka. Foto/Toho
A
A
A
JAKARTA - Tahun 2003. Berselang empat tahun setelah tragedi Columbine High School, Gus Van Sant merilis film yang memperlihatkan dua perspektif dari sebuah peristiwa berjudul Elephant.
Tragedi Columbine High School membuat seantero Amerika syok, nyaris sebanding dengan 'kerusakan' yang ditimbulkan oleh tragedi 11 September. Reaksi masyarakat Amerika berbeda–beda terhadap tragedi tersebut.
Sineas seperti Michael Moore memilih mengangkatnya ke layar lebar dalam bentuk film dokumenter, Bowling For Columbine.Sementara Gus Van Sant menyodorkan Elephant yang memilih mereka ulang keseharian sebelum tragedi tersebut terjadi.
Nyaris hingga 45 menit sejak film dimulai, tak terjadi apa–apa. Kamera hanya merekam siswa–siswi berjalan di sepanjang hall sekolah, bergosip, saling menyapa. Juga menyorot salah seorang pelaku bermain piano selama sepuluh menit.
Yang luar biasa adalah ketika Gus mengulang keseluruhan adegan dengan perpektif yang beda. Rasanya, Gus ingin memperlihatkan kemajemukan sudut pandang seseorang terhadap sesuatu atau sekeliling. Dengan melihat suatu kejadian dari berbagai sudut pandang, bisa jadi kita akan mampu ‘melihat’ lebih jernih.
![CERMIN: Monster Itu Bernama Prasangka]()
Foto: Toho
Pilihan dua sudut pandang yang diambil Gus di-upgrade oleh sineas Jepang, Hirokazu Kore-eda dalam Monster. Kali ini ia membeberkan tiga sudut pandang sekaligus dari sebuah cerita yang diimbuhi dengan komentar sosialnya atas perjuangan ibu tunggal, isu LGBTQ, hingga kekerasan terhadap anak.
Karena sudah menyaksikan Elephant lebih daridua puluhtahun lalu, maka saya tak terlalu terpesona pada struktur cerita berlapis yang dibangun penulis skenario Yuji Sakamoto. Namun berbeda dengan Elephant yang cenderung meminimalisir dramatisasi, Monster justru mendorong ceritanya ke level dramatik yang menarik.
Kita bertemu dengan tokoh-tokohnya yang merasa gagal sebagai orang tua, merasa tak bisa dipahami sebagai remaja lelaki yang sedang puber, dan merasa sedang dihakimi atas kesalahan yang dituduhkan kepadanya. Kita bertemu Saori, seorang ibu tunggal yang mengasuh putranya seorang diri.
Dengan segala kesibukannya, Saori tetap menyempatkan waktu bercengkrama bersama anaknya. Ia mencari tahu segala kegiatannya termasuk hal-hal yang dilakukannya selama di sekolah.
Hingga Saori disergap prasangka bahwa telah terjadi sesuatu pada putranya. Ia tak mencoba mencari tahu lebih dalam tentang yang terjadi pada putranya, tahu-tahu ia sudah menyerbu sekolah dan guru-guru. Ia akhirnya menuduh putranya mengalami perbuatan tak menyenangkan yang dilakukan oleh seorang guru.
![CERMIN: Monster Itu Bernama Prasangka]()
Foto: Toho
Putranya, Minato, sesungguhnya sedang dalam dilema besar. Ia sedang mengalami masa puber, tak punya figur ayah dalam hidupnya dan sedang bingung dengan perasaannya. Tapi ia tak mungkin bercerita soal itu pada ibunya yang disangkanya mungkin tak akan bisa mengerti.
Ketika ibunya tahu-tahu sudah menyerbu sekolah dan menyidang guru-gurunya, Minato tak bisa berkata apa pun. Tahu-tahu gurunya, Pak Hori, menjadi korban dari prasangka itu.
Padahal Pak Hori adalah guru yang baik bagi Minato, juga bagi Yori, teman akrabnya. Pak Hori terjebak dalam pusaran prasangka, dan ia diminta mengakui kesalahan yang tak dilakukannya atau sekolah tempatnya mengajar akan berada dalam masalah besar.
Sebagaimana Close (2022) arahan Lukas Dhont, Hirokazu memberanikan diri menyentuh isu sensitif bagi anak atau remaja laki-laki. Sebagaimana Remi dalam Close, Minato juga bingung dengan yang ia rasakan.
Tak ada seseorang yang menjadi tempatnya untuk berbagi perasaan yang paling dalam. Ia tak mungkin bercerita ke ibunya, apalagi ke gurunya. Mungkin ia bisa bercerita pada ayahnya, sayangnya ayahnya sudah meninggal.
![CERMIN: Monster Itu Bernama Prasangka]()
Foto: Toho
Tapi Monster lebih dari sekadar isu tipis LGBTQ yang tersirat samar dalam filmnya. Monster juga terkoneksi dengan kita di mana pun karena relevan dengan yang kita alami keseharian. Sebagai orang tua tunggal, saya memahami rasanya menjadi Saori yang sering merasa gagal mendidik anak.
Sebagai seorang manusia, saya memahami rasanya menjadi Hori yang disalahpahami. Kita tahu hari-hari ini sering kali monster sesungguhnya dalam hidup kita adalah prasangka yang dengan mudah membelit pemikiran jernih kita, yang menggerakkan kita secara otomatis tanpa mempertimbangkan banyak hal sebelum menghakimi.
Mungkin itu pula yang menjadikan Monster beroleh keplokan meriah ketika diputar di berbagai festival bergengsi dan beroleh predikat prestisius, Best Screenplay, di Cannes. Karena Monster sekali lagi menyadarkan bahwa musuh yang perlu kita perangi bersama adalah monster bernama prasangka.
Suara dari Maya Angelou soal prasangka pun masih terdengar nyaring hingga hari ini. Dari soal politik hingga rumah tangga, prasangka selalu menjadi monster dulu, kini, dan nanti. emestinya kita sudah tahu cara mengantisipasinya.
“Prejudice is a burden that confuses the past, threatens the future and renders the present inaccessible”.
Monster
Produser: Megumi Banse, Minami Ichikawa, Taichi Ito, Ryo Ota, Hijiri Taguchi, Kiyoshi Taguchi, Hajime Ushioda, Kenji Yamada, Tatsumi Yoda
Sutradara: Hirokazu Kore-eda
Penulis Skenario: Yuji Sakamoto
Pemain: Sakura Ando, Soya Kurokawa, Eita Nagayama
Ichwan Persada
Sutradara/produser/penulis skenario, pernah menjadi dosen di Universitas Padjajaran dan SAE Institute, bisa dikontak via Instagram @ichwanpersada
Tragedi Columbine High School membuat seantero Amerika syok, nyaris sebanding dengan 'kerusakan' yang ditimbulkan oleh tragedi 11 September. Reaksi masyarakat Amerika berbeda–beda terhadap tragedi tersebut.
Sineas seperti Michael Moore memilih mengangkatnya ke layar lebar dalam bentuk film dokumenter, Bowling For Columbine.Sementara Gus Van Sant menyodorkan Elephant yang memilih mereka ulang keseharian sebelum tragedi tersebut terjadi.
Nyaris hingga 45 menit sejak film dimulai, tak terjadi apa–apa. Kamera hanya merekam siswa–siswi berjalan di sepanjang hall sekolah, bergosip, saling menyapa. Juga menyorot salah seorang pelaku bermain piano selama sepuluh menit.
Yang luar biasa adalah ketika Gus mengulang keseluruhan adegan dengan perpektif yang beda. Rasanya, Gus ingin memperlihatkan kemajemukan sudut pandang seseorang terhadap sesuatu atau sekeliling. Dengan melihat suatu kejadian dari berbagai sudut pandang, bisa jadi kita akan mampu ‘melihat’ lebih jernih.

Foto: Toho
Pilihan dua sudut pandang yang diambil Gus di-upgrade oleh sineas Jepang, Hirokazu Kore-eda dalam Monster. Kali ini ia membeberkan tiga sudut pandang sekaligus dari sebuah cerita yang diimbuhi dengan komentar sosialnya atas perjuangan ibu tunggal, isu LGBTQ, hingga kekerasan terhadap anak.
Karena sudah menyaksikan Elephant lebih daridua puluhtahun lalu, maka saya tak terlalu terpesona pada struktur cerita berlapis yang dibangun penulis skenario Yuji Sakamoto. Namun berbeda dengan Elephant yang cenderung meminimalisir dramatisasi, Monster justru mendorong ceritanya ke level dramatik yang menarik.
Kita bertemu dengan tokoh-tokohnya yang merasa gagal sebagai orang tua, merasa tak bisa dipahami sebagai remaja lelaki yang sedang puber, dan merasa sedang dihakimi atas kesalahan yang dituduhkan kepadanya. Kita bertemu Saori, seorang ibu tunggal yang mengasuh putranya seorang diri.
Dengan segala kesibukannya, Saori tetap menyempatkan waktu bercengkrama bersama anaknya. Ia mencari tahu segala kegiatannya termasuk hal-hal yang dilakukannya selama di sekolah.
Hingga Saori disergap prasangka bahwa telah terjadi sesuatu pada putranya. Ia tak mencoba mencari tahu lebih dalam tentang yang terjadi pada putranya, tahu-tahu ia sudah menyerbu sekolah dan guru-guru. Ia akhirnya menuduh putranya mengalami perbuatan tak menyenangkan yang dilakukan oleh seorang guru.

Foto: Toho
Putranya, Minato, sesungguhnya sedang dalam dilema besar. Ia sedang mengalami masa puber, tak punya figur ayah dalam hidupnya dan sedang bingung dengan perasaannya. Tapi ia tak mungkin bercerita soal itu pada ibunya yang disangkanya mungkin tak akan bisa mengerti.
Ketika ibunya tahu-tahu sudah menyerbu sekolah dan menyidang guru-gurunya, Minato tak bisa berkata apa pun. Tahu-tahu gurunya, Pak Hori, menjadi korban dari prasangka itu.
Padahal Pak Hori adalah guru yang baik bagi Minato, juga bagi Yori, teman akrabnya. Pak Hori terjebak dalam pusaran prasangka, dan ia diminta mengakui kesalahan yang tak dilakukannya atau sekolah tempatnya mengajar akan berada dalam masalah besar.
Sebagaimana Close (2022) arahan Lukas Dhont, Hirokazu memberanikan diri menyentuh isu sensitif bagi anak atau remaja laki-laki. Sebagaimana Remi dalam Close, Minato juga bingung dengan yang ia rasakan.
Tak ada seseorang yang menjadi tempatnya untuk berbagi perasaan yang paling dalam. Ia tak mungkin bercerita ke ibunya, apalagi ke gurunya. Mungkin ia bisa bercerita pada ayahnya, sayangnya ayahnya sudah meninggal.

Foto: Toho
Tapi Monster lebih dari sekadar isu tipis LGBTQ yang tersirat samar dalam filmnya. Monster juga terkoneksi dengan kita di mana pun karena relevan dengan yang kita alami keseharian. Sebagai orang tua tunggal, saya memahami rasanya menjadi Saori yang sering merasa gagal mendidik anak.
Sebagai seorang manusia, saya memahami rasanya menjadi Hori yang disalahpahami. Kita tahu hari-hari ini sering kali monster sesungguhnya dalam hidup kita adalah prasangka yang dengan mudah membelit pemikiran jernih kita, yang menggerakkan kita secara otomatis tanpa mempertimbangkan banyak hal sebelum menghakimi.
Mungkin itu pula yang menjadikan Monster beroleh keplokan meriah ketika diputar di berbagai festival bergengsi dan beroleh predikat prestisius, Best Screenplay, di Cannes. Karena Monster sekali lagi menyadarkan bahwa musuh yang perlu kita perangi bersama adalah monster bernama prasangka.
Suara dari Maya Angelou soal prasangka pun masih terdengar nyaring hingga hari ini. Dari soal politik hingga rumah tangga, prasangka selalu menjadi monster dulu, kini, dan nanti. emestinya kita sudah tahu cara mengantisipasinya.
“Prejudice is a burden that confuses the past, threatens the future and renders the present inaccessible”.
Monster
Produser: Megumi Banse, Minami Ichikawa, Taichi Ito, Ryo Ota, Hijiri Taguchi, Kiyoshi Taguchi, Hajime Ushioda, Kenji Yamada, Tatsumi Yoda
Sutradara: Hirokazu Kore-eda
Penulis Skenario: Yuji Sakamoto
Pemain: Sakura Ando, Soya Kurokawa, Eita Nagayama
Ichwan Persada
Sutradara/produser/penulis skenario, pernah menjadi dosen di Universitas Padjajaran dan SAE Institute, bisa dikontak via Instagram @ichwanpersada
(ita)